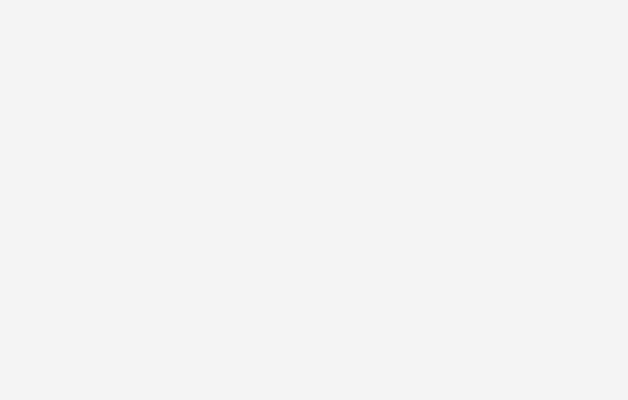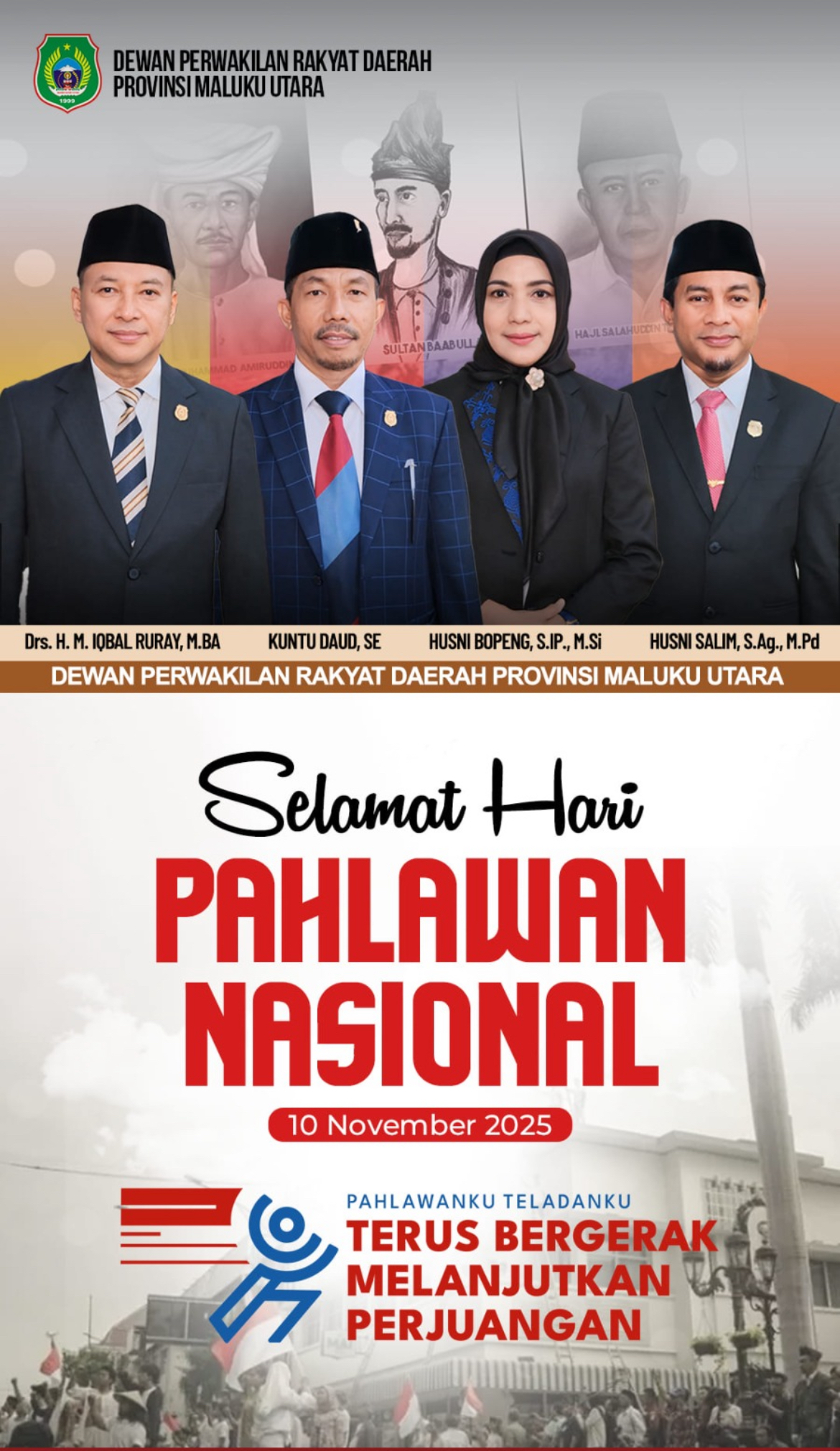IRONI SEKOLAH GRATIS

Herman Oesman
Dosen Sosiologi FISIP UMMU
Dalam benak banyak orang tua di pelosok negeri ini, “sekolah gratis” merupakan mantra yang membawa harapan. Ia bagaikan mata air di padang gersang, menjanjikan kesegaran hidup bagi generasi mendatang, bagi sebagian anak yang merindukan untuk bersekolah. Namun, sebagaimana harapan acapkali bertabrakan dengan kenyataan, istilah “gratis” ternyata tak sesederhana bunyi yang dikandungnya.
Sejak dicanangkannya Program Wajib Belajar 9 Tahun oleh pemerintah Orde Baru, lalu diperluas menjadi 12 tahun oleh pemerintahan setelah reformasi, konsep sekolah gratis selalu menjadi janji politik. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, negara menekankan pentingnya pendidikan dasar sebagai fondasi bangsa. Bahkan, UUD 1945 Pasal 31 (ayat 2) menyebut : bahwa “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.
Namun, menurut penuturan M. Nuh, mantan Menteri Pendidikan Nasional, yang dikutip dari Kompas (2010), pendidikan gratis tidak serta-merta berarti tiada biaya sama sekali. Ia lebih mengarah pada pembebasan pungutan rutin dan biaya SPP, sedangkan pembiayaan lain seperti seragam, transportasi, dan les tambahan tetap menjadi tanggungan keluarga.
Luka dalam Narasi
Dari desa/kelurahan di pelosok Halmahera, Ternate, Tidore, Morotai, Sula, Taliabu hingga gang-gang sempit di kota-kota besar, realitas sekolah gratis menunjukkan sebuah ironi yang menganga lebar.
Di banyak sekolah negeri, SD dan SMP, kita kerap mendengar ibu-ibu rumah tangga bercerita dan berceloteh : “Katanya gratis, tapi seragam harus beli, fotokopi harus bayar, iuran kelas setiap bulan juga tetap ada.” Cerita dan celoteh semacam ini membentang luas di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam kajian SMERU Research Institute (2021), banyak sekolah yang, demi menutupi kekurangan dana operasional, tetap meminta “sumbangan sukarela” yang tidak sepenuhnya sukarela. Dalam laporan itu disebutkan bahwa 63% orang tua siswa masih mengeluarkan biaya tambahan untuk sekolah negeri dasar dan menengah, dengan rata-rata pengeluaran tahunan mencapai Rp 1,8 juta (lihat laporan SMERU, 2021 : 14).
Kaitan dengan ini, sosiolog Pierre Bourdieu (1986) dalam teorinya tentang “habitus dan kapital” menyatakan, bahwa sistem pendidikan acapkali mereproduksi ketimpangan sosial. Sekolah yang katanya gratis tetap menyisakan pintu-pintu sempit yang sulit ditembus anak-anak dari kelas bawah. Mereka mungkin duduk di kelas yang sama, tapi tidak mengakses bimbingan belajar privat, gawai untuk belajar daring, atau makanan bergizi saat istirahat. Dalam hal ini, pendidikan tak netral. Ia beroperasi dalam struktur kuasa dan modal.
Sekolah gratis merupakan hak sebagaimana amanat UUD 1945, bukan kemurahan hati negara. Meminjam pandangan Paulo Freire (1970), pendidikan sejati merupakan upaya membebaskan manusia dari penindasan struktural. Maka, jika pendidikan hanya mengganti biaya sekolah dengan serangkaian beban tersembunyi, maka yang terjadi bukanlah pembebasan, melainkan pelanggengan ketimpangan.
Untuk itu, perlu reposisi terhadap kebijakan pendidikan. Negara harus hadir secara utuh: bukan hanya membebaskan biaya SPP, tapi juga menjamin kebutuhan penunjang belajar. Sekolah gratis tak boleh berhenti di poster kampanye, tetapi harus menjadi kenyataan hidup yang dirasakan hingga ke pelosok desa.
Janji yang Ditepati
Di mimbar kampanye saat Pilkada lalu, kepala daerah menghamburkan janji sekolah gratis, namun berjalannya waktu, dan di ujung hari nanti, anak-anak bangsa akan menatap masa depan dari bangku-bangku sekolah mereka. Mereka membawa harapan keluarga, dan disinilah, seharusnya, negara dan pemerintah menggendong tanggung jawab itu.
Sekolah gratis bukan tentang ketiadaan pungutan semata, tapi tentang keadilan dalam mengakses mimpi. Jika negara sungguh ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, maka ia harus lebih dari sekadar menjanjikan. Ia harus memastikan dan ditunaikan.[]