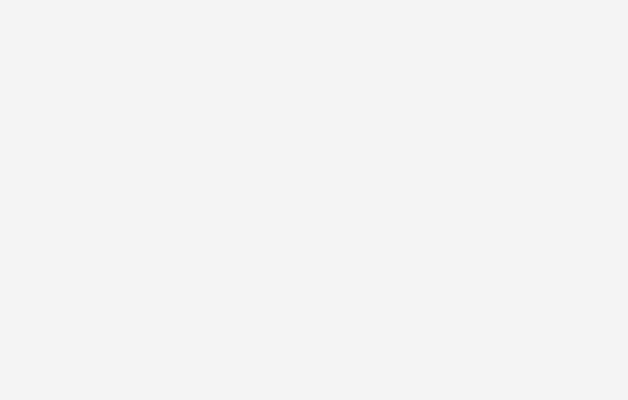Membaca Kutukan Sumber Daya Alam

Oleh : Idrus E. Maneke
Mahasiswa S2 Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) Jakarta.
Fenomena negara atau daerah yang kaya sumber daya alam namun gagal mewujudkan kesejahteraan sosial bukanlah hal baru dalam kajian ilmu sosial dan politik. Banyak wilayah dengan cadangan minyak, gas, mineral, dan hasil tambang lainnya justru terjebak dalam kemiskinan struktural, konflik sosial, kerusakan lingkungan, serta lemahnya institusi demokrasi. Paradoks ini dikenal luas sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam.
Tulisan ini menggunakan pemikiran Michael L. Ross, salah satu ilmuwan politik terkemuka, untuk memberikan analisis mendalam tentang bagaimana kekayaan sumber daya alam, khususnya minyak dan mineral, dapat melemahkan tata kelola pemerintahan jika tidak dikelola secara transparan dan akuntabel. Dari pemikiran Ross ini, kita juga dapat mengaitkannya dengan tata kelola terutama yang ada di wilayah tambang (nikel).
Michael L. Ross, melalui bukunya The Oil Curse... (2012) menegaskan bahwa masalah utama bukan terletak pada keberadaan sumber daya alam itu sendiri, melainkan pada cara negara mengelolanya. Dalam banyak kasus, ketergantungan terhadap pendapatan ekstraktif mendorong negara bersikap malas secara institusional. Pemerintah tidak lagi terdorong membangun basis pajak yang sehat karena pendapatan dapat diperoleh secara cepat dari rente sumber daya. Akibatnya, relasi antara negara dan warga melemah, sebab pajak, yang seharusnya menjadi mekanisme akuntabilitas, kehilangan perannya sebagai alat kontrol publik.
Dalam kerangka pemikiran inilah, menurut Ross, lemahnya tata kelola di negara atau daerah kaya sumber daya beroperasi melalui beberapa mekanisme kunci. _Pertama_ adalah rentier effect, yakni kondisi ketika negara menggantungkan anggaran pada rente sumber daya sehingga tidak merasa perlu merespons tuntutan masyarakat. Negara menjadi kuat secara fiskal, tetapi lemah secara demokratis. _Kedua_ adalah repression effect, di mana pendapatan besar memungkinkan negara membiayai aparat keamanan untuk meredam kritik dan perlawanan sosial. _Ketiga_ adalah modernization effect yang terhambat, karena sektor ekstraktif tidak menciptakan lapangan kerja luas atau mendorong diversifikasi ekonomi.
Kondisi ini menjelaskan mengapa banyak negara atau daerah yang kaya sumber daya mengalami stagnasi pembangunan manusia. Pendapatan negara yang besar tidak otomatis bertransformasi menjadi investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan inovasi. Ini yang sementara dialami beberapa daerah kaya sumber daya di Indonesia. Sebaliknya, dana tersebut sering kali terserap dalam proyek-proyek mercusuar, belanja birokrasi, atau bahkan korupsi elite. Dalam perspektif tata kelola, kekayaan sumber daya menciptakan peluang besar bagi praktik state capture, di mana kebijakan publik dikendalikan oleh kepentingan segelintir aktor politik dan ekonomi.
Ross juga melalui tulisannya yang lain, What Have We Learned about the Resource Curse? (2015) menekankan bahwa sektor ekstraktif cenderung bersifat eksklusif dan terpusat. Keputusan strategis mengenai kontrak tambang, bagi hasil, dan perizinan sering diambil di tingkat pusat tanpa partisipasi masyarakat lokal. Hal ini memicu konflik horizontal dan vertikal, terutama ketika masyarakat di wilayah tambang menanggung dampak ekologis dan sosial tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang sepadan. Dalam banyak kasus, masyarakat lokal justru mengalami pemiskinan ekologis, kehilangan tanah, air bersih, dan sumber penghidupan tradisional.
Dalam konteks tata kelola, transparansi menjadi isu krusial. Ross menunjukkan bahwa bagaimana negara dengan ketergantungan tinggi pada minyak dan mineral cenderung memiliki tingkat transparansi anggaran yang rendah. Informasi tentang penerimaan negara, kontrak pertambangan, dan alokasi dana sering tertutup dari publik. Ketertutupan ini memperlemah pengawasan masyarakat sipil dan lembaga legislatif, sekaligus memperbesar ruang bagi korupsi sistemik. Tanpa mekanisme keterbukaan, kekayaan sumber daya berubah menjadi sumber distorsi kebijakan publik.
Namun, Ross tidak bersikap deterministik. Ia menolak anggapan bahwa kutukan sumber daya adalah nasib yang tak terelakkan. Sejumlah negara, (misalnya, seperti Norwegia dan Botswana) menunjukkan bahwa tata kelola yang kuat dapat mengubah sumber daya alam menjadi berkah pembangunan. Kunci utamanya terletak pada institusi yang inklusif, sistem pajak yang sehat, pengelolaan dana publik yang transparan, serta komitmen politik untuk menjadikan sumber daya alam sebagai alat kesejahteraan jangka panjang, bukan sekadar sumber rente jangka pendek (Ross, 2012).
Dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa S2 Ilmu Politik, pemikiran Ross memberikan kerangka analitis yang penting untuk membaca problem pembangunan di negara berkembang, termasuk di tingkat daerah. Lemahnya tata kelola sumber daya bukan sekadar persoalan teknis administrasi, tetapi berkaitan erat dengan relasi kuasa, struktur ekonomi-politik, dan orientasi pembangunan. Tanpa reformasi institusional yang serius, kekayaan sumber daya justru akan memperdalam ketimpangan dan memperlemah legitimasi negara.
Dengan demikian, wacana negara atau daerah kaya sumber daya alam tapi lemah tata kelola, harus dipahami sebagai tantangan struktural. Mengacu pada Michael L. Ross, solusi tidak cukup dengan meningkatkan produksi atau investasi ekstraktif, melainkan dengan membangun tata kelola yang demokratis, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Tanpa itu, sumber daya alam akan terus menjadi sumber konflik, ketidakadilan, dan kegagalan pembangunan.(§)