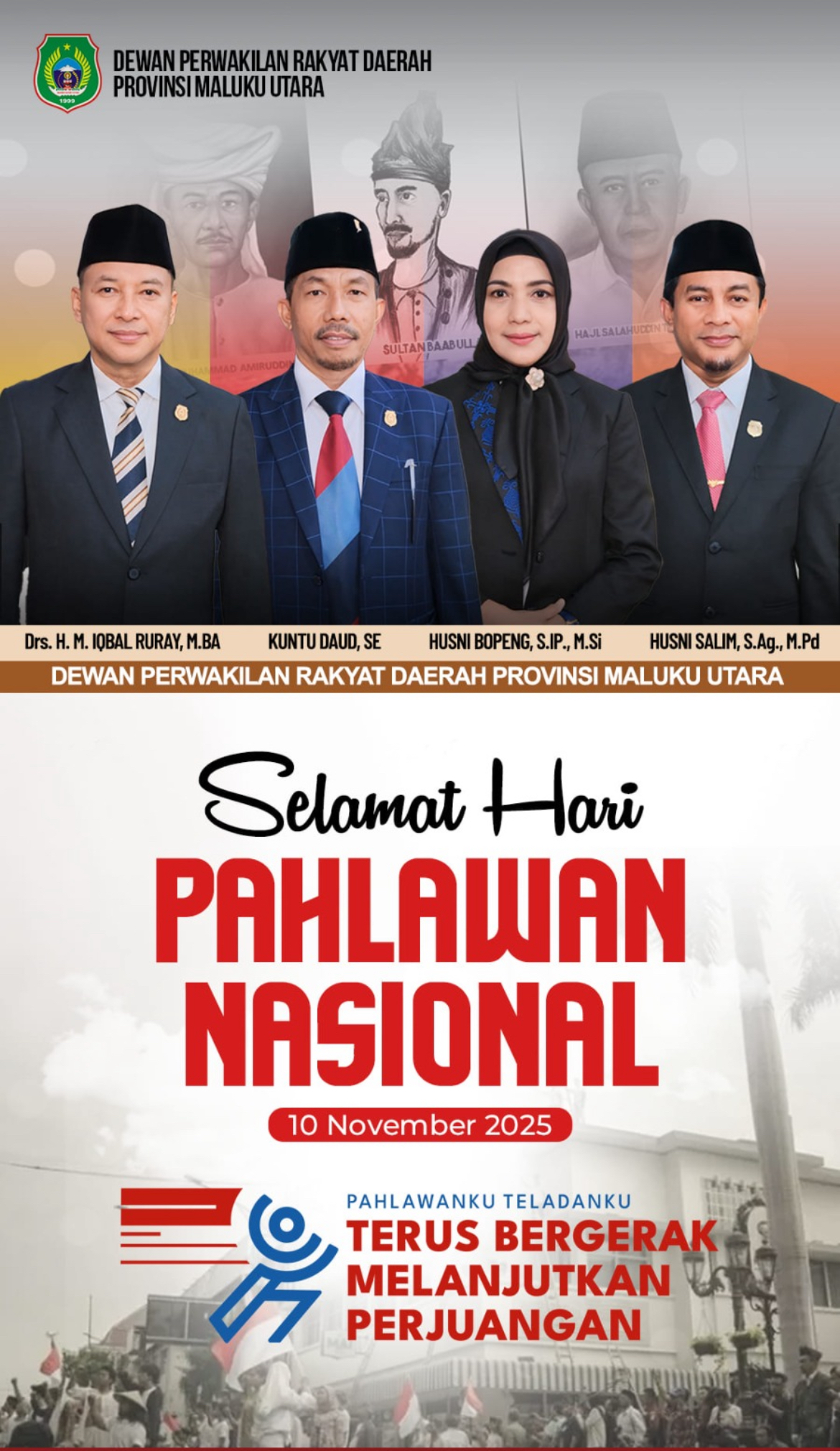Pendidikan Sebagai Strategi Kebudayaan

Dr. Kasman Hi. Ahmad, M.Pd
Wakil Bupati Halmahera Utara & Ketua ICMI Orwil Maluku Utara
Pendidikan sering kali dianggap sebagai instrumen utama mobilitas sosial dan pembangunan manusia. Namun, Pierre Bourdieu, seorang sosiolog Perancis terkemuka, menggugat pandangan idealis tersebut dengan menyatakan bahwa pendidikan tidak sekadar sarana pembebasan, melainkan juga strategi dominasi dan reproduksi struktur sosial melalui mekanisme kebudayaan. Perspektif ini menggugah kesadaran kritis terhadap bagaimana pendidikan dijalankan, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana kebudayaan dibentuk dan diwariskan melalui institusi pendidikan.
Menurut Bourdieu, pendidikan bukanlah ruang netral, melainkan medan (field) tempat berlangsungnya perebutan kekuasaan simbolik yang mempertahankan struktur kelas sosial (Bourdieu & Passeron, 1990, hlm. 5).
Bourdieu memperkenalkan konsep kunci seperti habitus. Konsep habitus merujuk pada skema mental dan disposisi yang dibentuk oleh pengalaman sosial individu sejak dini. Dalam konteks pendidikan, habitus siswa dari kelas sosial tertentu akan memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan sistem pendidikan. Anak-anak dari kelas menengah ke atas cenderung memiliki habitus yang selaras dengan nilai-nilai dominan di sekolah, seperti cara berbicara, cara berpikir logis, dan apresiasi terhadap seni atau ilmu pengetahuan. Sebaliknya, siswa dari kelas bawah sering kali mengalami ketidaksesuaian budaya yang menyebabkan mereka tertinggal dalam proses belajar (Bourdieu, 1986).
Hal ini berkaitan erat dengan modal kultural, yakni pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperoleh dari lingkungan keluarga dan sosial. Modal kultural terdiri dari tiga bentuk: inkorporasi (pengetahuan yang melekat dalam tubuh, seperti gaya berbicara), objektifikasi (buku, alat musik, dsb.), dan institusionalisasi (ijazah atau gelar). Sekolah cenderung menghargai modal kultural kelas dominan, dan dengan demikian mereproduksi ketimpangan sosial secara halus (Bourdieu, 1986, hlm. 244).
Bourdieu mengungkapkan bahwa pendidikan menjalankan fungsi utama sebagai alat reproduksi sosial. Sistem pendidikan mewariskan struktur sosial dari generasi ke generasi dengan menyamarkan kekuasaan sebagai sesuatu yang wajar dan sah.
Inilah yang disebut sebagai kekerasan simbolik, sebuah bentuk dominasi yang tidak menggunakan kekerasan fisik, melainkan melalui penanaman nilai-nilai dan makna yang diterima tanpa perlawanan (Bourdieu & Passeron, 1990, hlm. 4).
Misalnya, kurikulum pendidikan sering kali mencerminkan perspektif budaya dominan dan menyingkirkan kebudayaan lokal atau kelas bawah. Bahasa baku yang digunakan di sekolah sering kali berasal dari kelas atas dan meminggirkan dialek lokal, sehingga anak dari kelas bawah merasa tidak kompeten atau minder. Dalam kerangka ini, pendidikan tidak netral, tetapi merupakan medan pertarungan simbolik di mana kelompok dominan mempertahankan kekuasaan melalui legitimasi budaya (Bourdieu, 1977, hlm. 172).
Pendidikan sebagai Strategi Kebudayaan
Dengan demikian, pendidikan merupakan strategi kebudayaan dalam arti bahwa ia menjadi wahana bagi penguasaan makna dan simbol. Negara, sebagai agen dominan, menggunakan sistem pendidikan untuk menyebarluaskan nilai-nilai tertentu yang dianggap universal, padahal sesungguhnya merepresentasikan kepentingan kelompok tertentu. Proses ini disebut misrecognition—penerimaan nilai-nilai dominan sebagai netral dan adil padahal sesungguhnya tidak (Bourdieu, 1977, hlm. 164).
Namun demikian, Bourdieu tidak bersifat deterministik. Ia membuka ruang bagi perubahan dengan menekankan pentingnya kesadaran kritis terhadap mekanisme dominasi ini. Pendidikan bisa menjadi strategi emansipasi apabila mampu mengenali dan mengakui keragaman modal kultural, serta menciptakan ruang bagi kebudayaan alternatif dari kelompok yang selama ini dimarginalkan.
Dalam konteks Indonesia dan Maluku Utara, gagasan Bourdieu menantang kita untuk merefleksikan ulang sistem pendidikan nasional yang masih bias terhadap kelas sosial dan budaya dominan. Ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas, pemusatan kurikulum di Indonesia Barat, dan pengabaian bahasa daerah dalam proses pembelajaran menunjukkan bagaimana pendidikan mereproduksi ketimpangan sosial dan budaya.
Untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana perubahan sosial, diperlukan upaya dekonstruksi terhadap nilai-nilai dominan yang selama ini dianggap netral. Kurikulum harus dirancang inklusif, menghargai keberagaman kultural, serta mengakui modal kultural lokal sebagai bagian sah dari pengetahuan. Guru perlu diberdayakan sebagai agen kebudayaan yang tidak hanya mentransmisikan ilmu, tetapi juga membangun ruang dialog dan refleksi kritis.
Melalui perspektif Pierre Bourdieu, pendidikan dapat dipahami sebagai arena strategis di mana kebudayaan diproduksi, disebarluaskan, dan diperebutkan. Ia bukanlah ruang netral, melainkan alat dominasi simbolik yang mempertahankan struktur sosial yang ada. Namun justru karena sifatnya yang simbolik dan penuh makna, pendidikan juga menyimpan potensi transformatif jika dijalankan secara kritis dan inklusif.[]
BACA JUGA:“DI TANGAN GURU, MASA DEPAN PENDIDIKAN ITU DITULIS”