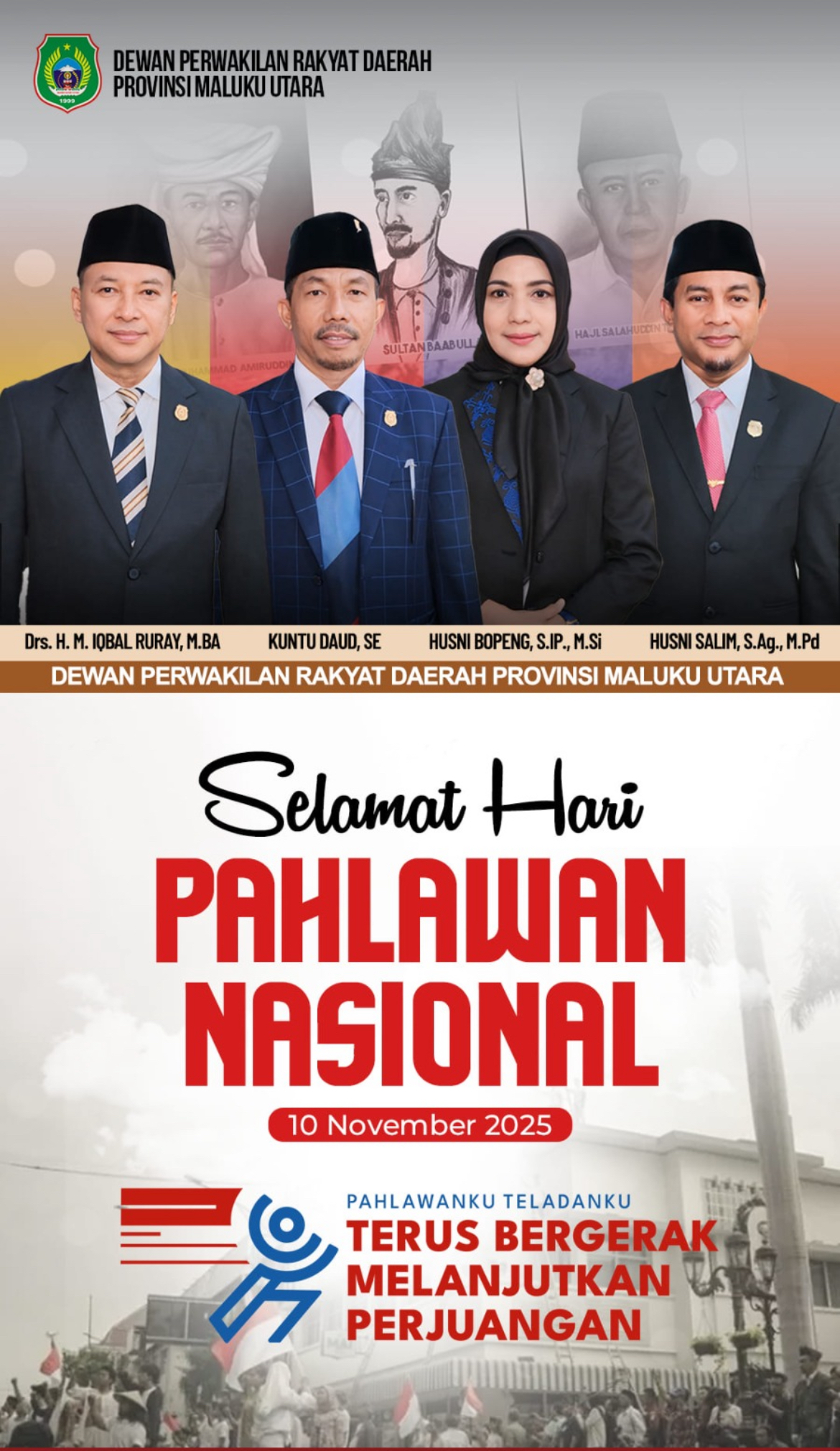TAFSIR SOSIOLOGI MUHAMMADIYAH

Herman Oesman
Dosen Sosiologi FISIP UMMU
_”Muhammadiyah harus senantiasa menjaga keseimbangan antara spirit purifikasi, pelayanan sosial, dan keterbukaan terhadap perubahan budaya”_
Muhammadiyah bukan sekadar gerakan dakwah, melainkan sebuah kekuatan transformasi sosial yang menggabungkan Islam modernis dengan praktik kemasyarakatan.
Sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat, sosiologi mengenal konsep-konsep penting, yakni interaksi sosial, dan institusi sosial, yang menyediakan kerangka analisis penting untuk memahami peran organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dalam dinamika sosial Indonesia.
Sebagai organisasi Islam modern tertua di Indonesia, Muhammadiyah telah memainkan peran besar dalam membentuk lanskap pendidikan, kesehatan, dan moralitas sosial bangsa Indonesia sejak awal abad ke-20.
Didirikan KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1912, Muhammadiyah lahir sebagai respons terhadap stagnasi umat Islam yang terbelakang secara sosial dan ekonomis dalam bayang-bayang kolonialisme Belanda.
Gerakan ini mengusung semangat purifikasi ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah, sekaligus mengadopsi pendekatan rasional dan ilmiah dalam memajukan kehidupan masyarakat.
Sejak awal, Muhammadiyah telah menunjukkan ciri khasnya sebagai gerakan sosial keagamaan yang bercorak modernis dan reformis (Nakamura, 1983 : 55).
Kemampuan Ahmad Dahlan memadukan ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan modern, membentuk cara pandang yang kritis dalam praktik keagamaan. Ia mengkritik praktik keagamaan yang dianggap tak berdasar dalil kuat dan menolak sinkretisme agama lokal.
Dalam kacamata sosiologi agama, Muhammadiyah, seperti dikemukakan Peter L. Berger, dapat dilihat sebagai agen rasionalisasi agama dalam masyarakat, mengurangi unsur mistik dan menggantikannya dengan rasionalitas normatif (Berger, 1990 : 131).
Dalam teori gerakan sosial klasik, sebagaimana dibahas oleh Charles Tilly, dalam Social Movement, 1768-2004, (2004), Tilly menjelaskan, gerakan sosial muncul dari struktur kesempatan politik dan jaringan sosial yang memungkinkan mobilisasi massa. Muhammadiyah memenuhi unsur ini dengan membentuk jaringan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang luas, terutama di Jawa dan kemudian meluas ke seluruh Indonesia.
Dalam konteks ini, Muhammadiyah bukan sekadar gerakan keagamaan, melainkan juga aktor pembangunan sosial berbasis komunitas.
Sebagai organisasi, Muhammadiyah mengembangkan amal usaha yang berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial. Sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan universitas yang dikelola Muhammadiyah menjadi simbol konkret kontribusi sosial organisasi ini.
Hal ini sejalan dengan teori struktural-fungsionalisme Talcott Parsons yang menekankan pentingnya institusi sosial dalam menjaga keteraturan dan stabilitas masyarakat (Parsons, 1951 : 342).
Salah satu aspek penting dalam sosiologi Muhammadiyah adalah bidang pendidikan. Di mana Muhammadiyah meyakini bahwa pendidikan merupakan kunci utama pembebasan umat dari keterbelakangan. Model pendidikan yang diterapkan Muhammadiyah, mencerminkan sintesis antara nilai-nilai Islam dan pengetahuan umum. Ini menjadikan sekolah Muhammadiyah sebagai ruang sosial untuk pembentukan kesadaran kolektif yang rasional, sebagaimana konsep collective consciousness (kesadaran kolektif) dari Emile Durkheim (1893/1997 : 102).
Dalam praktiknya, sistem pendidikan Muhammadiyah menanamkan nilai-nilai moral keislaman sekaligus ketrampilan hidup yang relevan dengan dunia modern. Pendidikan bukan hanya instrumen dakwah, tetapi juga alat mobilitas sosial vertikal bagi masyarakat Muslim kelas menengah dan bawah.
Di sisi lain, Muhammadiyah juga berhasil menciptakan apa yang disebut Antonio Gramsci sebagai hegemonik sosial kultural di kalangan umat Islam urban. Melalui kontrol terhadap wacana pendidikan dan moralitas, Muhammadiyah memainkan peran sebagai kelas intelektual organik dalam masyarakat Muslim Indonesia (lihat, Gramsci, 1971 : 333).
Sementara dari perspektif sosiologi transformasi sosial, Muhammadiyah merupakan contoh nyata bagaimana agama dapat menjadi kekuatan modernisasi. Gerakan ini telah berhasil menggeser pola pikir tradisional menuju masyarakat yang lebih rasional, terbuka terhadap kemajuan, dan berpijak pada etika kerja Islam.
Max Weber dalam The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (1905) menyatakan bahwa etika keagamaan dapat mendorong munculnya kapitalisme modern.
Dalam konteks Indonesia, Muhammadiyah menunjukkan bagaimana etika Islam bisa menjadi landasan bagi etos kerja produktif dan kemajuan ekonomi.
Selain itu, Muhammadiyah juga memperlihatkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan konteks politik dan sosial yang berubah. Dalam era Orde Baru, Muhammadiyah mengambil sikap kooperatif namun tetap menjaga jarak kritis.
Dalam reformasi 1998, kader Muhammadiyah aktif dalam konsolidasi demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak kaku dalam doktrin, tetapi lentur dalam strategi sosial-politik.
Di dalam Muhammadiyah, juga diciptakan identitas sosial khas bagi anggotanya. Sebagai komunitas iman dan amal, identitas Muhammadiyah terbentuk melalui simbol, gaya hidup, dan praktik sosial tertentu, mulai dari cara berpakaian, sistem pengajaran, hingga pandangan terhadap adat dan budaya. Sebagaimana dijelaskan Erving Goffman (1959), identitas sosial terbentuk melalui interaksi simbolik yang konsisten dalam ruang sosial tertentu.
Sikap puritan namun progresif membuat warga Muhammadiyah memiliki identitas yang berbeda dibandingkan kelompok keagamaan lain. Mereka dikenal sebagai kelompok yang bersih, teratur, mandiri, dan berorientasi kemajuan. Identitas ini terus direproduksi melalui sistem kaderisasi dan pengajian rutin, menciptakan semacam habitus, dalam arti pemikiran Bourdieu, yaitu struktur mental dan sosial yang mengarahkan tindakan dan persepsi individu dalam komunitasnya (Bourdieu, 1984 : 170).
Kritik Sosiologis
Meski banyak kontribusi positif, dari sudut pandang kritis, Muhammadiyah juga menghadapi tantangan internal. _Pertama_, kecenderungan elitis di kalangan pimpinan dan akademisi Muhammadiyah dapat menciptakan jarak dengan umat akar rumput. _Kedua_, semangat purifikasi kadang menimbulkan eksklusivisme yang menghambat dialog budaya. _Ketiga_, birokratisasi dalam amal usaha Muhammadiyah kerap dianggap menjauh dari semangat gerakan sosial yang organik dan partisipatif.
Dalam perspektif sosiologi kritis, hal ini menandakan terjadinya institusionalisasi gerakan keagamaan yang bisa melemahkan daya transformasinya. Sebagaimana ditunjukkan Jurgen Habermas (1984), ketika rasionalitas sistem mendominasi rasionalitas komunikatif, maka tujuan-tujuan emansipatoris dapat tergantikan oleh kepentingan administrasi dan kekuasaan.
Muhammadiyah merupakan contoh nyata bagaimana organisasi Islam yang dapat memainkan peran sentral dalam proses transformasi sosial melalui pendekatan modern, rasional, dan berorientasi pelayanan publik. Dalam kerangka sosiologis, Muhammadiyah dapat dipahami sebagai institusi sosial keagamaan yang multifungsi, menciptakan struktur pendidikan, membentuk identitas kolektif, serta menjadi aktor dalam perubahan sosial. Namun, agar tetap relevan di masa depan, Muhammadiyah harus terus menjaga keseimbangan antara spirit purifikasi, pelayanan sosial, dan keterbukaan terhadap perubahan budaya, Go Ahead Muhammadiyah.[]