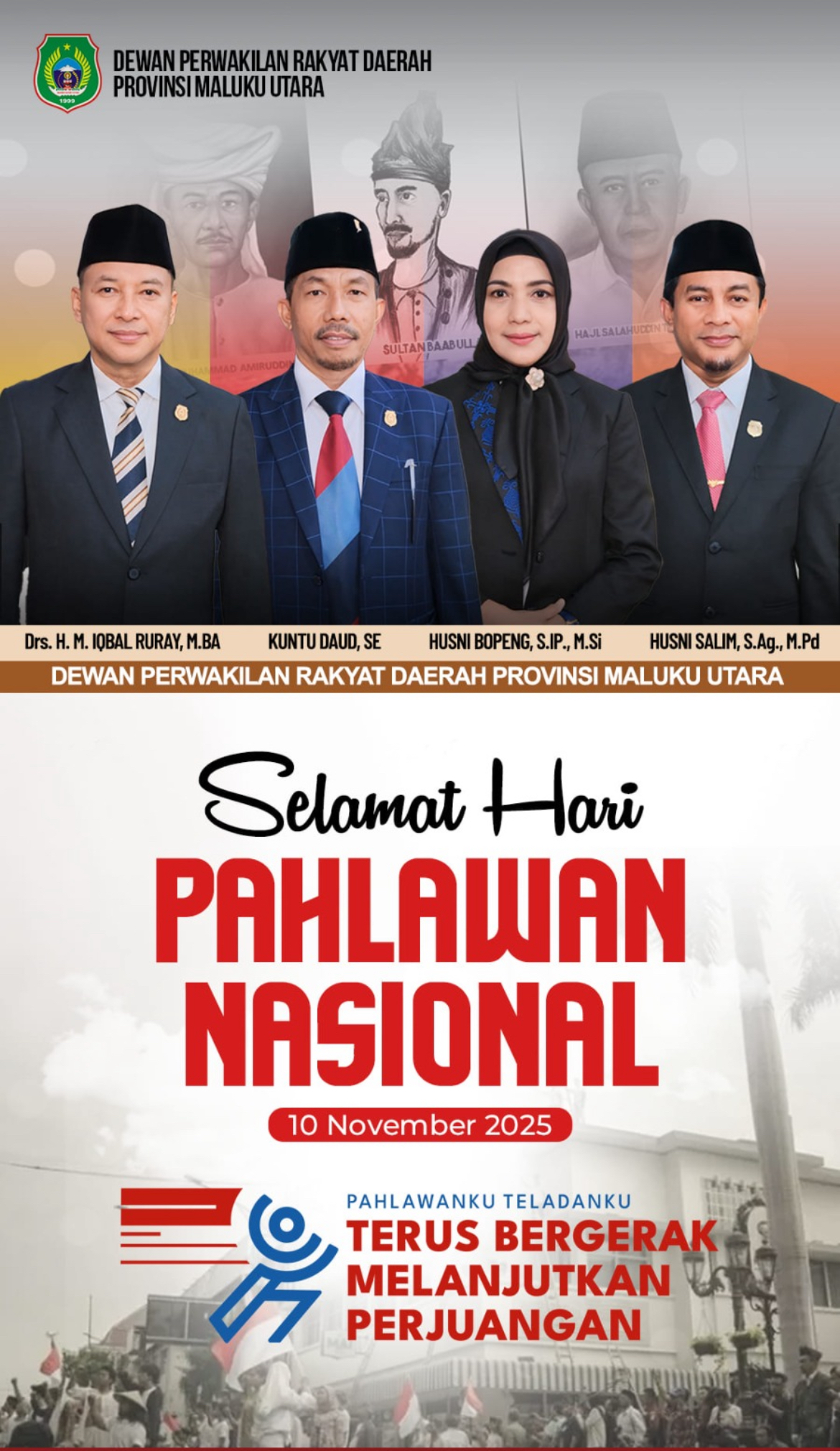MOHOLEHE

Herman Oesman
Dosen Sosiologi FISIP UMMU
Dalam bentang kehidupan kepulauan Halmahera nan eksotik, terdapat sosok perempuan yang selalu hadir sebagai penjaga harmoni antara manusia dan alam. Itulah moholehe. Perempuan Halmahera dengan simbol keteguhan, kearifan, dan keintiman spiritual dengan bumi yang memberi kehidupan. Dalam bahasa Tobelo, “moholehe” dapat dimaknai sebagai perempuan yang selain cantik, juga memiliki keteguhan atau kuat hati. Tidak sekadar dalam arti fisik, melainkan kekuatan batin yang berakar pada nilai-nilai lokal, spiritualitas, dan kedekatan ekologis dengan tanah leluhur.
Di banyak komunitas adat di Halmahera, alam bukan hanya ruang hidup (lebensraum), tetapi juga entitas hidup yang memiliki jiwa (anima). Alam menjadi bagian dari keluarga besar manusia, di mana hutan, laut, dan tanah dianggap sebagai “ina” (ibu). Moholehe tumbuh dalam pandangan ini. Ia memahami bahwa tanah tidak boleh diperlakukan sebagai benda mati, melainkan sumber kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya.
Dalam sebuah riset etnografi tentang masyarakat Tobelo, disebutkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menjaga hubungan dengan “tanah dan air,” dua unsur yang dianggap sebagai roh penopang kehidupan. Moholehe mewarisi pemahaman ini melalui praktik sehari-hari : menanam keladi, ubi, dan pisang, mengumpulkan daun obat (rorano), menjaga api di tungku agar tak padam, dan mengajarkan kepada anak-anak bahwa alam memiliki telinga dan mata.
Seperti yang diuraikan Arturo Escobar dalam bukunya Designs for the Pluriverse, menandaskan, masyarakat adat yang dekat dengan alam membangun kosmologi relasional, bahwa manusia dan alam merupakan satu kesatuan yang saling mencipta dan saling menjaga (Escobar, 2018: 36).
Dalam kosmologi ini, moholehe bukan sekadar aktor sosial, tetapi penjaga nilai keberlanjutan.
Keteguhan moholehe terlihat dalam caranya mempertahankan nilai-nilai lokal di tengah perubahan sosial yang deras. Modernisasi dan penetrasi industri ekstraktif di Halmahera, terutama pertambangan nikel, mengancam sistem nilai dan relasi ekologis masyarakat. Namun, moholehe menolak tunduk pada arus yang melunturkan makna hidup mereka.
Tania Murray Li menyatakan, ekspansi kapital di wilayah-wilayah adat kerap meminggirkan peran perempuan yang selama ini menjadi pengelola sumber daya alam secara berkelanjutan (Li, 2014:97).
Di Halmahera, moholehe menjadi suara penyeimbang dalam komunitasnya. Ia menolak tanah leluhur dijual untuk kepentingan tambang, dengan alasan bahwa tanah bukan hanya sumber ekonomi, tetapi sumber moral dan spiritual.
Keteguhan ini bukan sekadar sikap politik, tetapi juga ekspresi etika hidup. Dalam istilah lokal, “menjaga rumah” memiliki makna luas: menjaga rumah berarti menjaga hutan, sungai, dan laut, sebab di sanalah rumah spiritual orang Halmahera. Nilai ini dihidupi moholehe dalam setiap tindakan kecil : menolak menebang pohon (termasuk sagu) dan lainnya, menanam kembali setiap pohon yang ditebang, dan mengingatkan generasi muda agar tidak membuang sampah di sungai. Ini adalah pantangan sekaligus nilai etis alam yang ada dalam jiwa batin moholehe Halmahera.
Kedekatan moholehe dengan alam tidak bisa dipisahkan dari spiritualitasnya. Dalam pandangan masyarakat Halmahera, setiap perempuan memiliki “roh penjaga” yang menghubungkan- nya dengan alam. Roh ini dipercaya menuntun mereka dalam membaca tanda-tanda alam : kapan waktu menanam, kapan laut akan bergelora, atau kapan hujan pertama akan turun. Sebuah pengetahuan lokal yang secara sahih dapat dikaji secara ilmiah.
Sebuah riset menunjukkan bahwa, pengetahuan ekologis perempuan Halmahera diwariskan secara turun-temurun, bukan melalui teks, tetapi melalui ritual dan simbol. Moholehe, misalnya, belajar dari ibunya tentang bagaimana menjaga alam dari lingkungan rumahnya, bagaimana praktik menandai waktu panen berdasarkan bintang yang muncul di langit timur. Semua itu menjadi pelajaran yang menghunjam dalam pikiran dan tindakan moholehe.
Dalam perspektif ekofeminisme, sebagaimana dijelaskan Vandana Shiva dalam Staying Alive: Women, Ecology and Development, menyatakan, perempuan memiliki hubungan eksistensial dengan bumi karena keduanya menjadi sumber kehidupan
(Shiva, 2010: 55).
Karenanya, eksploitasi terhadap alam sejatinya merupakan eksploitasi terhadap perempuan. Maka, perjuangan moholehe menjaga hutan dan air merupakan bentuk perlawanan terhadap patriarki ekologis yang datang bersama kapitalisme.
Dalam dua dekade terakhir, Halmahera menjadi pusat perhatian nasional karena geliat industri nikel yang menjadi bagian dari rantai pasok global baterai listrik, juga emas. Di sisi lain, perubahan ini membawa dampak sosial yang kompleks : degradasi lingkungan, konflik agraria, dan migrasi tenaga kerja dari luar daerah, yang mengempaskan anak negeri ke pinggiran sebagai penonton.
Bagi moholehe, tantangan ini bukan sekadar tentang kehilangan ruang hidup, tetapi kehilangan makna hidup. Ia menyadari bahwa nilai-nilai adat seperti : “menjaga tanah”, “menjaga rumah,” dan “menjaga kampung,” mulai tergerus oleh logika ekonomi pasar. Namun, mereka tidak berhenti bersuara.
Dalam sebuah catatan empirik, perempuan Halmahera menyebut diri mereka sebagai figur-figur moholehe, figur “penjaga kehidupan,” mereka yang berani menolak uang ganti rugi tanah tambang dan memilih tetap bertani di lahan kecil mereka. Tindakan ini merupakan bentuk perlawanan moral terhadap sistem yang mengukur segala sesuatu dengan nilai uang.
Moholehe merupakan representasi dari etika pulau (island ethics), sebuah cara pandang yang melihat dunia sebagai jejaring relasi antara manusia, alam, dan spiritualitas. Dalam sosiologi kepulauan, perempuan menjadi “penyangga nilai” yang menautkan ekologi dan moralitas dalam ruang sosial yang cair dan berubah.
Keteguhan moholehe bukan hanya kisah pribadi, tetapi cermin dari kekuatan kolektif mereka, kekuatan perempuan Halmahera yang hidup di antara laut dan gunung, di antara perubahan dan keberlanjutan. Ia mengajarkan bahwa menjaga alam adalah menjaga diri sendiri; bahwa nilai-nilai lokal bukan sisa masa lalu, melainkan panduan menuju masa depan yang lebih beradab.
Dalam dunia yang semakin bising oleh mesin dan uang, suara lembut moholehe yang memanggil anak-anaknya untuk menanam pohon, dan tentu menanam sagu, serta menimba air dari sungai terdengar seperti doa yang menyesap jauh ke jiwa, doa agar Halmahera tetap menjadi rumah yang hidup, teduh, dan bermartabat.[]