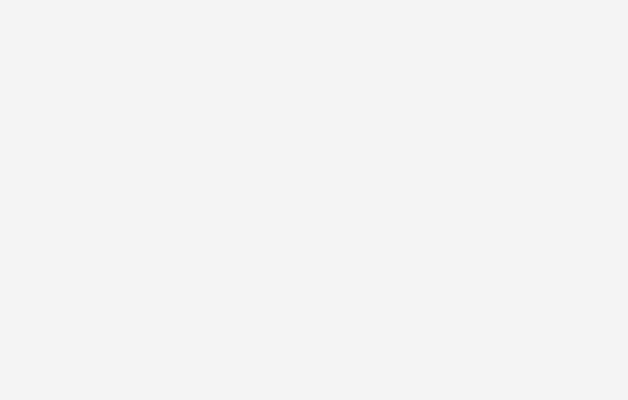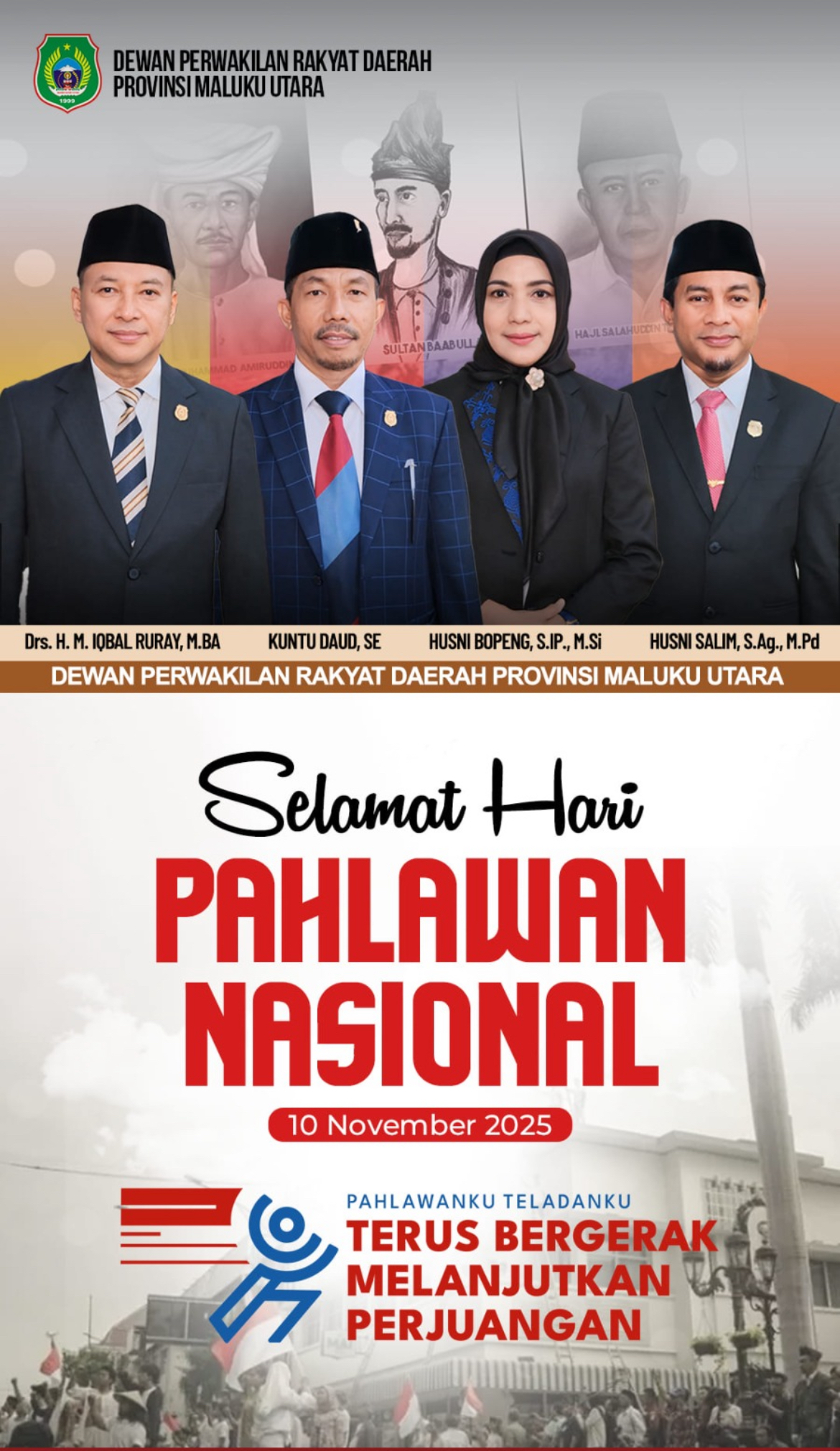KEMISKINAN YANG DIPELIHARA

Herman Oesman
Dosen Sosiologi FISIP UMMU
_”Kemiskinan yang dipelihara bukanlah mitos. Ia nyata dalam praktik kebijakan, dalam pola pembangunan, dan dalam relasi sosial-politik.“_
Kemiskinan kerap diposisikan sebagai masalah sosial yang harus diberantas. Namun dalam praktiknya, banyak kebijakan justru cenderung memelihara kemiskinan daripada mengatasinya. Bukan semata-mata karena ketidakefisienan pemerintah atau minimnya sumber daya, tetapi karena adanya relasi kuasa dan kepentingan ekonomi-politik yang melanggengkan struktur ketimpangan.
Dalam konteks ini, kemiskinan tidak lagi hanya dipahami sebagai keadaan kekurangan, tetapi sebagai hasil dari praktik sosial dan politik yang terstruktur.
Kemiskinan juga acapkali dilihat sebagai kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pendekatan ini cenderung menyalahkan individu atas kemiskinannya. Namun, teori struktural menjelaskan, bahwa kemiskinan merupakan hasil dari ketimpangan sistemik. Kekerasan struktural terjadi ketika sistem sosial dan ekonomi menghalangi individu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Galtung, 1990 : 291).
Dalam konteks ini, kemiskinan bukan sekadar kekurangan, melainkan ketidakadilan yang dilembagakan melalui struktur sosial dan ekonomi yang timpang.
Misalnya, program-program bantuan sosial yang bersifat karitatif kerap tidak menyentuh akar persoalan seperti distribusi lahan, akses pendidikan berkualitas, atau kesempatan kerja yang layak. Program semacam itu justru menciptakan ketergantungan dan memperkuat posisi dominan negara sebagai penyedia, bukan sebagai fasilitator pemberdayaan.
Politik Memelihara Kemiskinan
Dalam banyak kasus, kemiskinan menjadi komoditas politik. Di masa pemilu, narasi “membantu orang miskin” menjadi alat mobilisasi suara. Program bantuan langsung tunai (BLT) atau program sembako misalnya, kerap digulirkan tanpa mekanisme pemberdayaan yang berkelanjutan. Negara, demikian James C. Scott, kerap memainkan “politik penglihatan,” di mana intervensi yang terlihat (visible interventions) dianggap cukup, sementara struktur yang tidak terlihat tetap dibiarkan (Scott, 1990 : 45).
Politik patronase berkembang di tengah masyarakat miskin melalui relasi pertukaran antara bantuan dan dukungan politik. Dalam kondisi ini, keberadaan masyarakat miskin menjadi aset elektoral yang harus “dipelihara.” Artinya, kemiskinan dipertahankan agar dapat terus dimobilisasi sebagai bagian dari strategi kekuasaan.
Salah satu penyebab kemiskinan struktural adalah model pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya alam yang tidak inklusif. Negara-negara dengan institusi ekstraktif—yakni lembaga yang dirancang untuk mengeksploitasi sumber daya tanpa membagi hasilnya secara adil—akan terus gagal menghapus kemiskinan (Acemoglu & Robinson, 2012 : 74).
Di Indonesia, banyak daerah kaya sumber daya justru menjadi kantong kemiskinan. Halmahera, Papua, dan Kutai Kartanegara merupakan contoh nyata. Pendapatan daerah meningkat dari royalti tambang, namun masyarakat lokal tetap miskin karena tidak terlibat dalam proses produksi dan distribusi kekayaan. Dana CSR atau program tanggung jawab sosial perusahaan lebih acapkali menjadi alat pencitraan dibanding alat transformasi sosial.
Fenomena lain yang memperkuat kemiskinan terpelihara adalah tumbuhnya industri amal (charity industry). Lembaga-lembaga non-pemerintah dan organisasi kemanusiaan terkadang memperlakukan kemiskinan sebagai proyek berkelanjutan. Mereka lebih fokus pada distribusi bantuan daripada mendorong transformasi sosial.
Ini memperkuat kritik Slavoj Zizek terhadap bentuk bantuan modern yang lebih memperkuat status quo daripada mengubah struktur ketidakadilan (Zizek, 2009 : 20).
Dengan kata lain, kemiskinan menjadi ekosistem di mana banyak aktor mendapatkan keuntungan: politisi, pengusaha, LSM, bahkan akademisi. Kemiskinan bukan lagi “masalah” yang harus diselesaikan, melainkan realitas yang “berguna” untuk dilanggengkan.
Mengatasi kemiskinan tidak cukup dengan bantuan langsung. Diperlukan perubahan paradigma menuju pendekatan pemberdayaan berbasis hak (rights-based approach). Ini berarti mengembalikan kontrol atas sumber daya kepada masyarakat, menciptakan akses terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas, serta memperkuat ekonomi lokal berbasis komunitas. Amartya Sen menyebut hal ini sebagai “pembangunan sebagai kebebasan,” di mana masyarakat miskin diberi kemampuan untuk menentukan nasib sendiri (Sen, 1999 : 36).
Mendorong koperasi, memperkuat UMKM, mereformasi akses tanah dan distribusi aset produktif merupakan langkah strategis untuk membongkar struktur yang memelihara kemiskinan. Namun, hal ini hanya mungkin terjadi bila negara dengan tulus, sekali lagi, apabila negara secara tulus bersedia membongkar relasi kuasa yang timpang dan berani menolak kepentingan elite ekonomi-politik.
Kemiskinan yang dipelihara bukanlah mitos. Ia nyata dalam praktik kebijakan, dalam pola pembangunan, dan dalam relasi sosial-politik. Menghapus kemiskinan tidak cukup dengan niat baik, tetapi memerlukan keberanian politik untuk membongkar struktur yang melanggengkan nya. Tanpa perubahan mendasar, upaya pengentasan kemiskinan hanya akan menjadi panggung simbolik dalam lakon panjang ketimpangan.[]