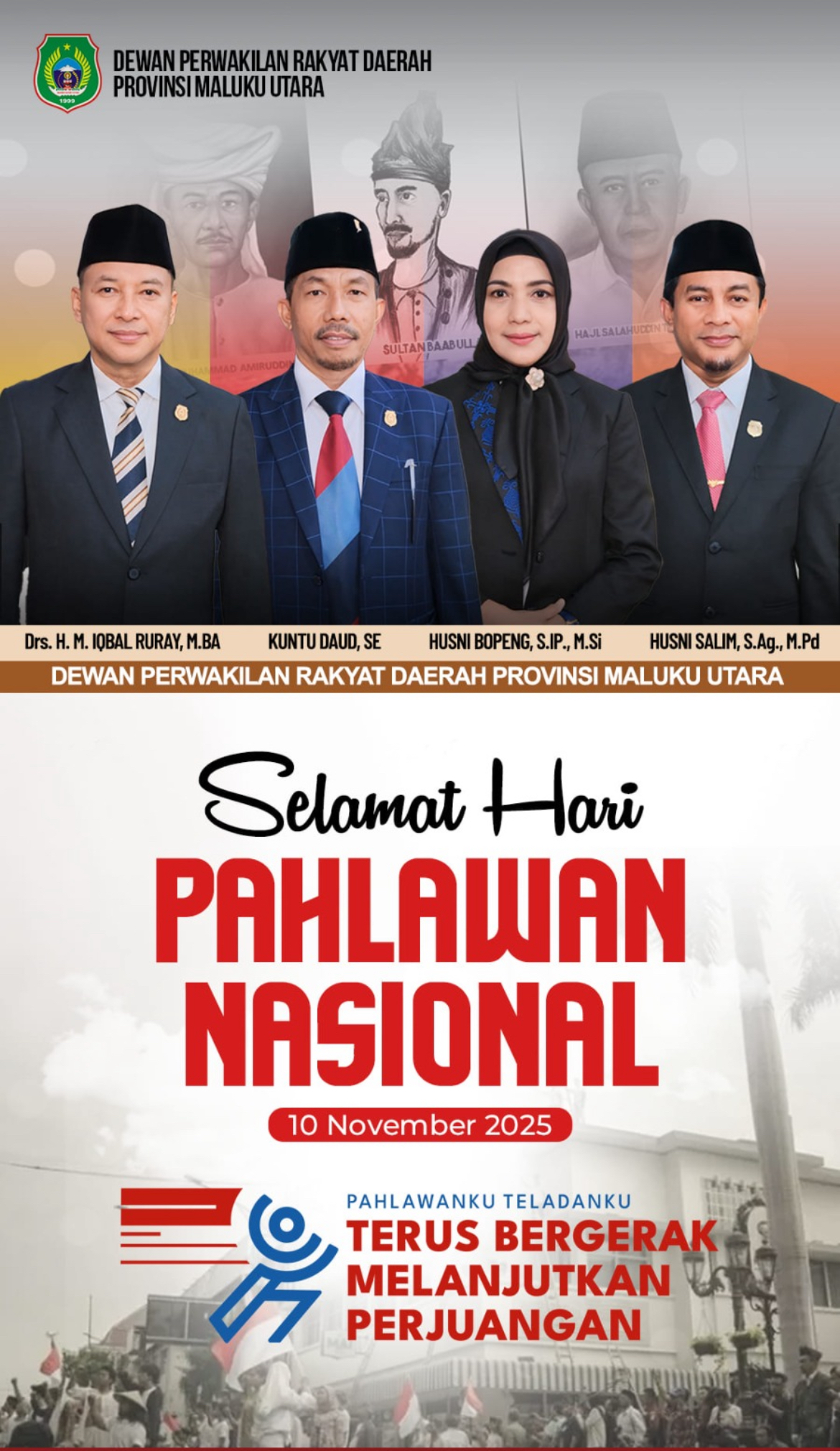“Jangan Jual Pulau Kami”

Herman Oesman
Dosen Sosiologi FISIP UMMU
_”…mari mendengar suara dari pesisir, dari para perempuan yang menjemur ikan, dari anak-anak mereka yang berlari di pasir…”_
“Pulau bukan sekadar tanah, ia rumah bagi roh leluhur, tempat anak-anak bermain, dan ladang harapan masa depan…” Itu suara lirih yang kerap terdengar jauh. Suara itu kini tenggelam dalam dengungan mesin tambang, lobi-lobi modal asing, naskah perizinan yang diteken jauh dari pantai, dan jauh dari nafas serak anak-anak pulau yang didera batuk. Atas nama kesejahteraan, keputusan itu diambil di balik meja-meja kebijakan yang dingin.
Pulau-pulau kecil di Indonesia, terutama di wilayah timur seperti Maluku Utara, kini berdiri di persimpangan sejarah. Di satu sisi, mereka adalah penjaga warisan ekologi dan budaya; di sisi lain, mereka digoda oleh janji-janji pembangunan yang menjelma dalam bentuk pertambangan, pariwisata eksklusif, atau bahkan penjualan pulau secara utuh kepada investor asing.
Isu jual beli pulau bukan sekadar wacana kosong. Sejak 2010-an, berbagai platform daring menampilkan iklan penjualan pulau di Indonesia. Misalnya, situs Private Islands Inc. secara terbuka menawarkan pulau-pulau seperti Gili Tangkong dan Pulau Tojo untuk dibeli oleh individu kaya dari luar negeri (Tempo, 2017). Bukan cuma di luar Maluku Utara, isu “penjualan” pulau di kawasan Halmahera juga kerap terdengar bising di media sosial.
Narasi penjualan ini kerap dibungkus dengan kata “pengembangan,” namun di balik itu tersembunyi realitas perampasan ruang hidup.
Bagi masyarakat adat dan komunitas pesisir, pulau merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas kolektif. Sosiolog Maritim seperti McCall (1994) menekankan bahwa masyarakat pulau memiliki hubungan ekologis yang erat dengan lanskap mereka. Pulau bukan objek kosong, melainkan ruang hidup yang dibentuk melalui praktik, relasi sosial, dan nilai-nilai sakral. Ketika pulau dijual atau dikuasai korporasi, yang hilang bukan hanya tanah, tapi juga narasi, kenangan, dan masa depan.
Praktik penjualan pulau juga menimbulkan persoalan hukum dan kedaulatan. Dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pulau tidak boleh diperjualbelikan, hanya bisa dikelola melalui izin pemanfaatan. Namun, celah dalam hukum, serta praktik manipulatif di lapangan, membuka jalan bagi privatisasi terselubung.
Kapitalisme ekstraktif menjadi wajah baru kolonialisme. Dalam banyak kasus, investasi atas nama pembangunan justru menimbulkan kerusakan ekologis dan ketimpangan sosial.
Sebagai kasus, di salah satu pulau di Sulawesi Tenggara, izin tambang nikel menyebabkan konflik horizontal, pencemaran air, dan kriminalisasi warga yang menolak penggusuran (WALHI, 2021). Fenomena serupa mengintai banyak pulau kecil lainnya di Indonesia, termasuk di Halmahera dan kawasan lain di Maluku Utara.
David Harvey (2003) menyebut proses ini sebagai accumulation by dispossession, yakni akumulasi kapital dengan cara merampas sumber daya komunitas. Dalam konteks pulau-pulau kecil, disposesi terjadi melalui pengambilalihan ruang laut dan darat, penghapusan hak-hak adat, serta penghancuran ekosistem yang menopang kehidupan.
Namun, narasi ini tidak hanya berisi duka. Dari pesisir hingga ke kota, gelombang perlawanan menguat. Komunitas di beberapa pulau di Indonesia menolak tambang emas skala besar karena mengancam sumber air dan wilayah kelola yang ditempati warga.
Warga yang terancam itu, berkata : “Kami bukan anti pembangunan, tapi kami menolak pembangunan yang membunuh kehidupan” (Lihat, Koalisi Save Sangihe Island, 2021).
Resistensi ini menunjukkan bahwa masyarakat pulau bukan objek pasif. Mereka merupakan subjek sejarah yang mempertahankan hak atas tanah dan lautnya. Dalam semangat inilah, seruan “Jangan Jual Pulau Kami!” menggema bukan hanya sebagai slogan, tetapi sebagai panggilan untuk meninjau ulang arah pembangunan bangsa.
Kita perlu beralih dari paradigma pembangunan yang eksploitatif ke arah ekologi keadilan. Hal ini mencakup pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal, perlindungan atas wilayah adat, dan pengelolaan sumber daya secara partisipatif dan berkelanjutan.
Joseph Stiglitz (2012) mengingatkan, bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan sosial dan ekologis hanya akan memperdalam krisis. Dalam konteks Indonesia, pembangunan yang adil harus memperhatikan suara dari pulau-pulau kecil, bukan hanya suara elite kota. Jika tidak, kita hanya akan mewariskan tanah rusak dan laut tercemar kepada generasi berikutnya.
Pulau-pulau itu bukan untuk dijual. Mereka merupakan pelabuhan kasih, penjaga sejarah, dan ruang hidup yang penuh makna. Menjualnya sama dengan menjual ruh bangsa.
Semoga tak ada pulau di Maluku Utara yang dijual.
Maka, mari mendengar suara dari pesisir, dari para perempuan yang menjemur ikan, dari anak-anak yang berlari di pasir, dari para tetua yang masih percaya bahwa laut adalah ibu, dan bersama mereka kita berseru: “Jangan jual pulau kami!”[]
BACA JUGA:Kartini dan Suara Lirih dari Rahim Ibu Bumi