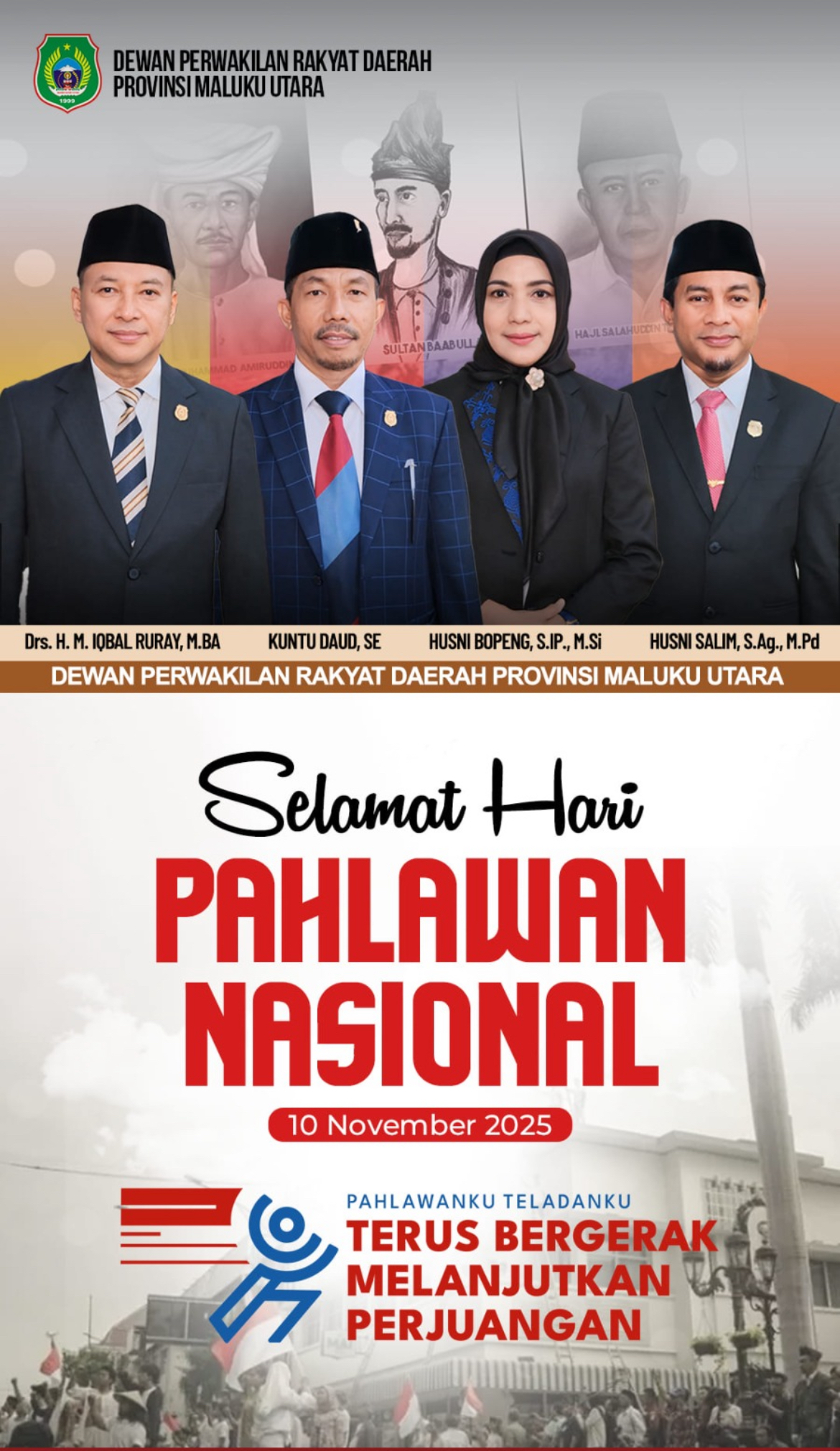Sosiologi Sebagai Kisah Manusia

Herman Oesman
Dosen Sosiologi FISIP UMMU
Sosiologi hadir bukan sebagai ilmu yang berdiri jauh di menara gading. Melainkan sebagai cermin yang merefleksikan kehidupan manusia sehari-hari. Di sinilah pentingnya memahami imajinasi sosiologi, sebagai jembatan yang menghubungkan dosen dan mahasiswa yang mempelajari sosiologi dengan dunia yang demikian kompleks.
Sosiologi tidak hanya bicara tentang teori; ia merupakan narasi tentang manusia dan masyarakat. Sosiolog C. Wright Mills, menyebutnya sebagai imajinasi sosiologi (sociological imagination), yakni suatu kemampuan untuk melihat hubungan antara pengalaman pribadi dan struktur sosial yang lebih luas (Mills, 1959 : 5). Dalam memahami sosiologi, imajinasi ini menjadi nyala api yang menghidupkan teks, menyalakan keingintahuan, menyulam realitas dengan kata-kata, dan memantik kesadaran akan dunia yang tak pernah sepenuhnya netral.
Sebagaimana ditulis Mills : “buah pertama dari imajinasi ini-dan pelajaran pertama dari ilmu sosial yang mewujudkannya, adalah gagasan bahwa individu dapat memahami pengalamannya sendiri dan mengukur nasibnya sendiri hanya dengan menempatkan dirinya dalam kurun waktunya”(Mills, 1959 : 6).
Sosiologi menjadi medan di mana mahasiswa sosiologi dapat belajar menempatkan diri dalam sejarah, dalam struktur, dalam konteks.
Bagi mahasiswa sosiologi, dan mereka yang mempelajari dan memahaminya, sosiologi kerap menjadi medan tempur antara logika ilmiah dan keinginan untuk menyampaikan suara hati. Namun justru di situlah kekuatannya.
Sebagaimana ditegaskan Peter Berger dalam bukunya, Invitation to Sociology yang mengajak kita memandang sosiologi sebagai petualangan intelektual yang penuh ironi, ketajaman, dan kadang, keindahan naratif (Berger, 1963 : 13–17).
Karena itu, menyampaikan tentang sosiologi yang baik tidak hanya menyampaikan data; tetapi ia harus mampu menggugah rasa ingin tahu. Ia membuat yang “biasa” menjadi “luar biasa”. Sebuah obrolan warung kopi bisa menjadi refleksi tentang kelas sosial.
Katakanlah sebuah antrean panjang di kantor pemerintahan yang melakukan pelayanan publik, dapat menjadi kisah tentang birokrasi dan kuasa, yang dapat dinarasikan dengan penuh kekuatan deskripsi. Inilah cara sosiologi berbicara dalam bahasa yang renyah, tapi tak kehilangan kedalamannya.
Memahami sosiologi bagi mahasiswa, sebaiknya dimulai dari hal-hal yang dekat, hal-hal kecil disekitarnya : keluarga, sekolah, tempat kost, pasar, media sosial. Ini sejalan dengan apa yang ditulis Anthony Giddens dalam bukunya, Sociology, di mana Giddens menekankan, pentingnya pemahaman terhadap tindakan sosial yang diulang-ulang, sebagai bagian dari struktur yang lebih besar (Giddens, 2006:13–15).
Melalui pemahaman sosiologi, mahasiswa diajak untuk menyingkap struktur itu melalui pengalaman personal.
Misalnya, menulis tentang pasar tradisional bukan hanya soal ekonomi, melainkan tentang jejaring sosial, gender, dan nilai-nilai budaya lokal. Mahasiswa harus dilatih membuka cakrawala pikirnya melalui tulisan, melalui imajinasi. Dan itu berarti, dosen harus siap dengan perkakas yang cukup untuk membawa mahasiswa menjelajahi alam kehidupan sosiologi.
Memahami akan sosiologi juga berarti berkomitmen pada suatu etika: etika melihat yang tertindas, yang tak terdengar, yang disingkirkan. Inilah yang oleh Paulo Freire (1970) mengajarkan bahwa refleksi kritis merupakan bagian dari pembebasan. Memahami realitas secara sosiologi dapat menjadi alat untuk menyuarakan yang bisu, menjelaskan yang rumit, dan membongkar kekuasaan yang tersembunyi.
Dalam memahami sosiologi, seorang dosen dan mahasiswa bisa menyusun imajinasi melalui esai tentang buruh kebun kelapa di wilayah Halmahera, atau nasib warga di kawasan industri, atau perebutan ruang di wilayah kota, bukan hanya dengan angka dan grafik, tetapi dengan narasi harian : peluh di bawah terik, cemas akan harga, dan impian sederhana tentang anak yang bisa sekolah, dan sebagainya. Di sinilah memahami dan menulis dengan imajinasi sosiologi akan menjadi ruang afeksi sekaligus intelektual.
Akhirnya, memahami dan menulis sosiologi bukan sekadar tugas perkuliahan yang rigid atau latihan akademik yang kaku. Ia merupakan bentuk awal dari tradisi berpikir kritis, yang kelak bisa menjadi gerakan, riset, atau kebijakan. Dengan memahami dan menulis imajinasi sosiologi, dosen dan mahasiswa tidak hanya memahami dunia—ia berpotensi mengubahnya, seperti kata Marx dalam Theses on Feuerbach (1845) : “Para filsuf hanya menafsirkan dunia, dengan berbagai cara; intinya, bagaimanapun juga, adalah untuk mengubahnya”.
Mari mengembangkan imajinasi sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. []