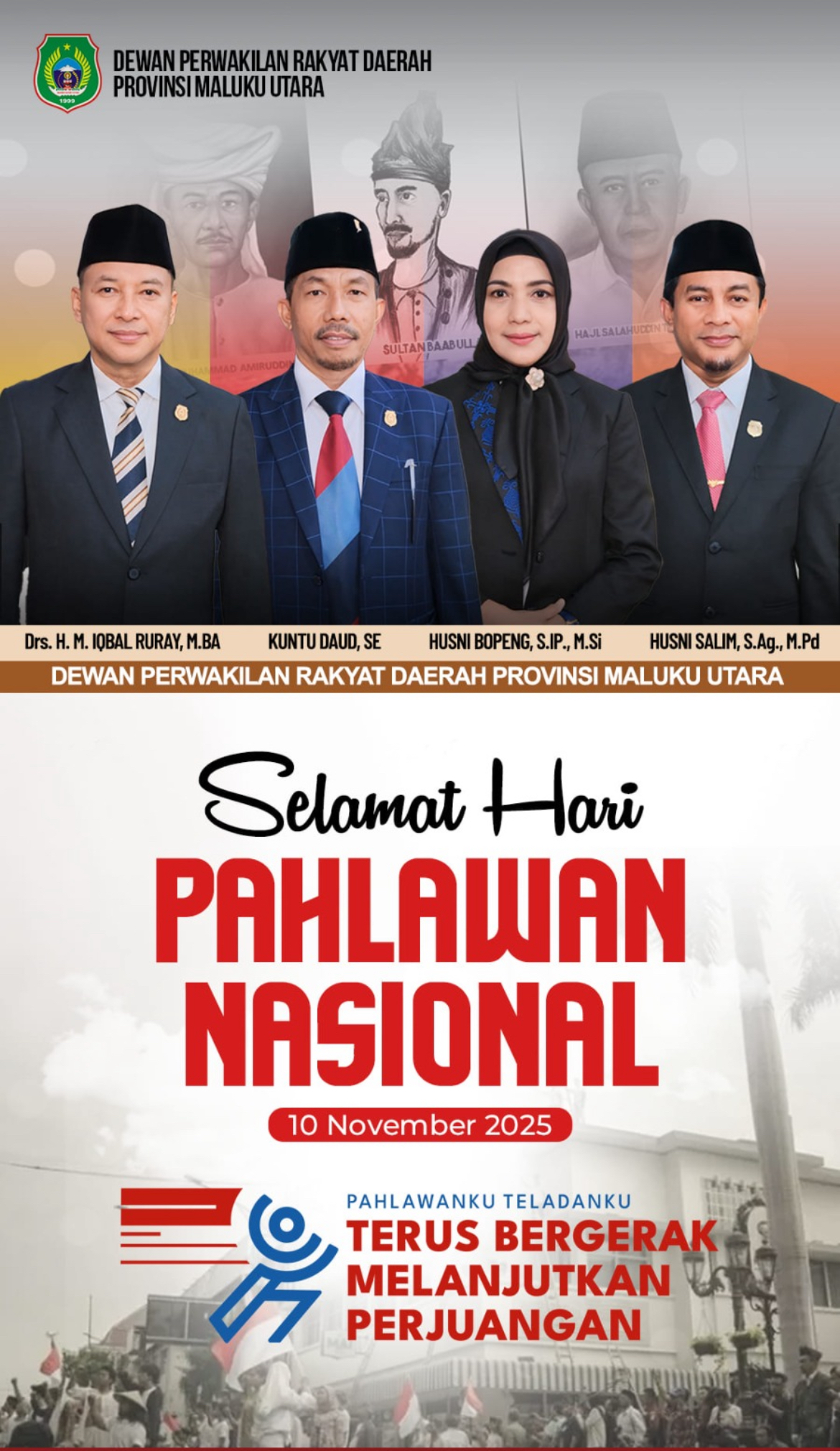“DI TANGAN GURU, MASA DEPAN PENDIDIKAN ITU DITULIS”

Herman Oesman
Dosen Sosiologi FISIP UMMU
_“Pendidikan berfungsi untuk menyatukan individu dalam kolektivitas, membentuk solidaritas sosial, dan memelihara tatanan moral”_
(Emile Durkheim, 1858-1917)
Di tengah waktu yang bergerak demikian cepat, kita sama menyaksikan wajah pendidikan yang berdiri sebagai benteng peradaban dengan begitu miris dan layu. Padahal, Ia merupakan nafas panjang yang tak pernah putus, meski diterpa gelombang perubahan sosial, teknologi, dan politik. Sementara di sana, terdapat sosok guru, yang setia dengan tugasnya. Guru telah menjadi lentera : cahaya kecil namun setia, menuntun manusia muda, membimbing anak bangsa meniti jalan kehidupan mereka.
Pendidikan bukan sekadar aktivitas mekanis untuk mentransfer ilmu, melainkan proses membentuk manusia seutuhnya. Sebagaimana dititahkan Ki Hadjar Dewantara (1967), pendidikan merupakan usaha memerdekakan manusia. Dalam kerangka ini, guru bukan sekadar pengajar (teacher), melainkan pendidik (educator) yang membangun jiwa peserta didik/murid, memperkaya pikiran, dan menanamkan budi pekerti bagi anak bangsa.
Seiring waktu, wajah pendidikan pun ikut berganti rupa. Di era Revolusi Industri dan Revolusi Digital, guru dihadapkan pada tantangan baru: teknologi yang perlahan mulai menggantikan banyak peran manusia. Namun sebagaimana penegasan Paulo Freire (1970), pendidikan sejatinya merupakan dialog; sebuah relasi dua arah, dua kutub, antara guru dan peserta didik/murid. Dalam dialog itu, guru tidak mengisi bejana kosong, melainkan membangkitkan kesadaran kritis bagi peserta didiknya.
Dari ruang kelas yang terkadang sempit, pengap, dan gaduh, guru itu membangun mimpi-mimpi kecil muridnya. Mereka menyulam harapan dalam benak anak-anak di desa dan di pulau yang mungkin tak pernah membayangkan bagaimana megah dan geriapnya kehidupan di kota, di kehidupan yang berbeda dengan apa yang mereka alami. Guru mengajarkan apa yang pernah dikonstatir Parker J. Palmer (1998), bahwa suatu pengajaran yang baik tidak dapat disederhanakan menjadi teknik; pengajaran yang baik ating dari identitas dan integritas guru.
Kualitas guru merupakan kualitas hati, bukan hanya kemampuan teknis. Sayangnya, dalam realitas sosial kita, penghargaan terhadap guru acapkali sebatas slogan. Padahal dalam sistem pendidikan yang kuat selalu bertumpu pada kesejahteraan dan kapasitas profesional guru (Menon, 2013). Tanpa perhatian serius terhadap nasib guru, pendidikan menjadi rapuh, kehilangan akarnya.
Di tengah dunia yang makin kompetitif, peran guru makin vital. Mereka bukan hanya pengajar ilmu, tetapi pengasah karakter. Pendidikan pada abad ke-21 ini, di era yang makin rentan secara digital, sangat dituntut peserta didik untuk memiliki 4C : critical thinking (berpikir kritis), creativity (kreativitas), collaboration (kolaborasi), dan communication (komunikasi), gurulah menjadi fasilitator utama dalam proses 4C ini (lihat, Trilling & Fadel, 2009).
Maka, menghormati guru, bukanlah sekadar membungkukkan badan di Hari Pendidikan Nasional. Menghormati guru berarti membangun sistem yang adil bagi mereka : upah yang layak, pelatihan berkelanjutan, ruang kreatif untuk mengajar, dan penghargaan terhadap martabat profesinya.
Di sinilah, sosiologi mengajarkan kita untuk melihat pendidikan bukan hanya sebagai sistem pelajaran, tetapi sebagai struktur sosial yang kompleks. Di sana terdapat harapan, kekuasaan, dan bahkan reproduksi ideologi. Pendidikan dapat menjadi alat pembebasan atau justru penjinakan. Tergantung bagaimana kita merancang dan memaknainya. Namun, jangan lupa, dalam pendidikan ada peran besar guru. Di Hari Pendidikan Nasional ini, sejatinya, dibutuhkan kesadaran seluruh bangsa untuk menopang kaki-kaki guru agar kuat berdiri untuk menulis. Karena di tangan mereka, para guru, masa depan pendidikan itu ditulis dengan anggun. Dengan kapur putih, dengan kesabaran panjang, dengan cinta yang mungkin tak pernah habis, para guru itu terus menulis, menyalakan pijar lentera untuk dunia. Selamat Hari Pendidikan Nasional.[]