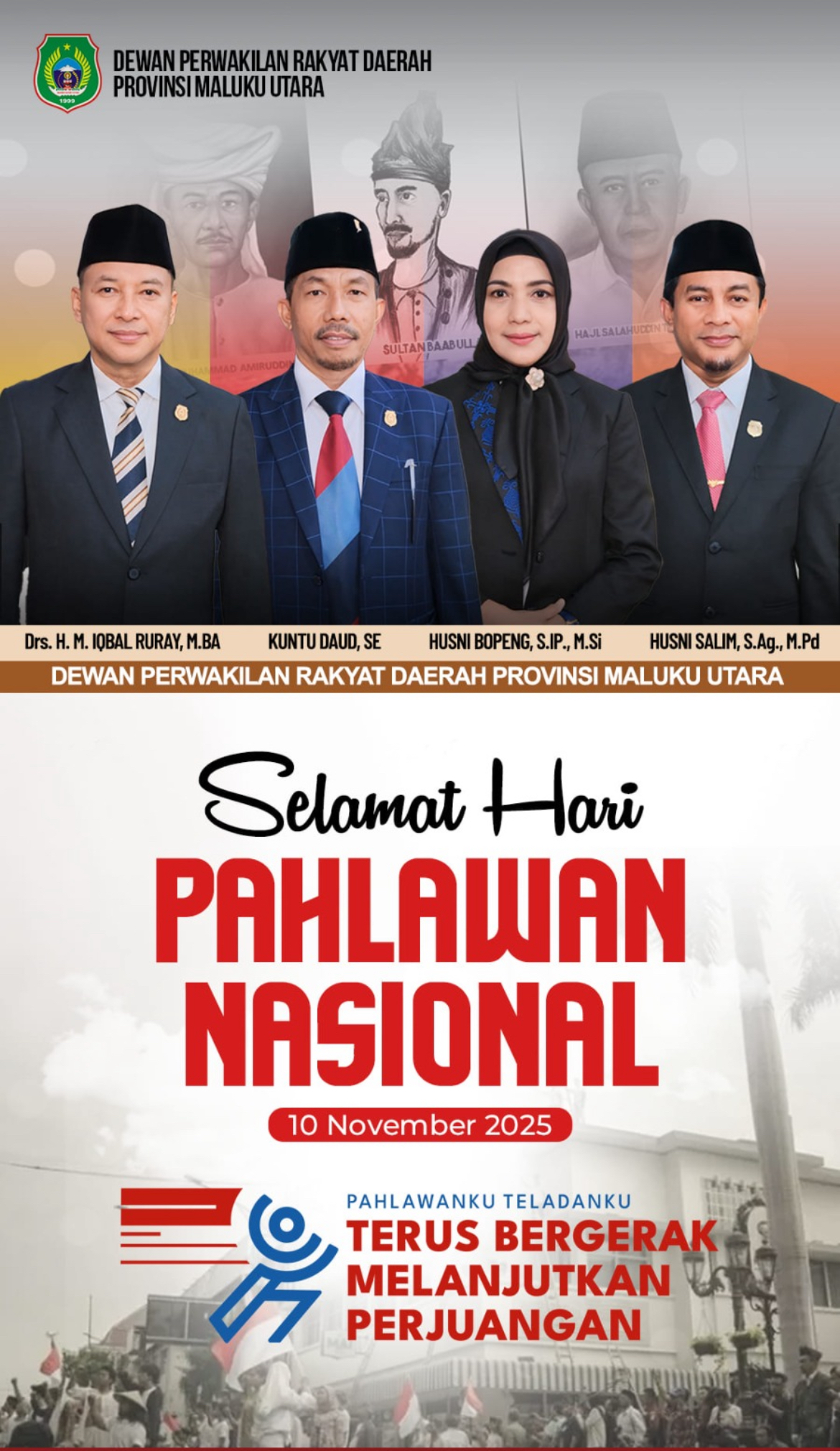Ketika Affan Jadi Martir

Herman Oesman
Dosen Sosiologi FISIP UMMU
“Affan Kurniawan kini menjadi bagian dari sejarah itu, sebuah pengingat bahwa keadilan kerap lahir dari pengorbanan.”
Kisah tentang seorang martir selalu lahir dari ketidakadilan sosial, politik, maupun ekonomi yang dialami sebuah masyarakat. Martir bukan sekadar korban, melainkan simbol perlawanan yang mengabadikan aspirasi kolektif. Affan Kurniawan, dalam konteks ini, menjadi representasi anak muda yang berhadapan langsung dengan kekuasaan yang menindas. Ketika Affan gugur, dilindas kendaraan rantis, ia tidak lagi hanya milik keluarga atau lingkungannya, melainkan milik sejarah yang lebih luas: sejarah perjuangan rakyat.
Dalam sosiologi politik, martir dipandang sebagai figur yang lahir dari konflik struktural. Mereka menjadi ikon yang menyeberangi batas personal menuju simbol perlawanan kolektif. Menurut Jeffrey C. Alexander, dalam karyanya :Cultural Trauma and Collective Identity menyatakan : “martyrdom transforms private death into a public narrative of sacrifice” [Kemartiran mengubah kematian pribadi menjadi narasi publik tentang pengorbanan]
(Alexander, 2004 : 93).
Dengan kata lain, gugurnya Affan bukan sekadar hilangnya seorang individu, tetapi ia menjadi “cerita publik” yang membentuk identitas kolektif masyarakat yang ditindas.
Affan mungkin hanyalah seorang anak muda biasa, driver ojek online (ojol), tetapi ketika realitas kekuasaan bertabrakan dengan semangat perubahan, tubuhnya menjadi arena perlawanan. Gugurnya Affan mengingatkan pada apa yang disebut Paulo Freire sebagai pedagogi penderitaan, di mana “kematian orang tertindas menghidupkan kesadaran baru bagi rakyat” (Freire, 1970 : 45).
Dalam banyak kasus di Indonesia, figur martir kerap lahir dari aksi-aksi massa. Misalnya, kasus mahasiswa yang gugur dalam demonstrasi reformasi 1998, seperti Elang Mulya Lesmana, dan kawan-kawannya, yang kemudian dikenang sebagai Pahlawan Reformasi. Mereka menandai bahwa perjuangan anak muda bukan sekadar resistensi sesaat, melainkan investasi sejarah.
Affan hadir dalam garis itu: ketika ia jatuh, suara-suara yang terbungkam bangkit. Ia menjadi martir yang memaksa masyarakat bertanya : “mengapa kekerasan terus berulang, dan mengapa negara kerap gagal melindungi rakyatnya?”
Affan telah menjadi martir. Martir, menurut Benedict Anderson, berfungsi sebagai “pengikat imajined community, yang mempersatukan orang-orang dalam narasi pengorbanan” (Anderson, 2006 : 204). Dalam konteks Affan, kematiannya dapat menjadi titik balik bagi gerakan sosial di lingkungannya.
Dari perspektif sosiologi emosi, hal ini dapat dikatakan : “kemarahan kolektif yang muncul dari penderitaan bersama acapkali menjadi energi terbesar gerakan sosial” (Jasper, 1997 : 106).
Affan menjadi simbol penderitaan itu, membangkitkan solidaritas, mengikat emosi massa, dan mengubahnya menjadi kekuatan politik.
Ketika Affan jadi martir, ia menyeberang dari dunia fana menuju ruang simbolik yang abadi. Tubuhnya mungkin gugur, tetapi semangatnya hidup dalam setiap teriakan keadilan. Martir merupakan paradoks: kematian satu orang dapat melahirkan kehidupan baru bagi banyak orang.
Seperti kata Frantz Fanon dalam bukunya The Wretched of the Earth, bahwa
“setiap kematian seorang pejuang merupakan awal kelahiran bangsa yang bebas” (Fanon, 1963 : 88).
Affan Kurniawan kini menjadi bagian dari sejarah itu, sebuah pengingat bahwa keadilan kerap lahir dari pengorbanan.[]