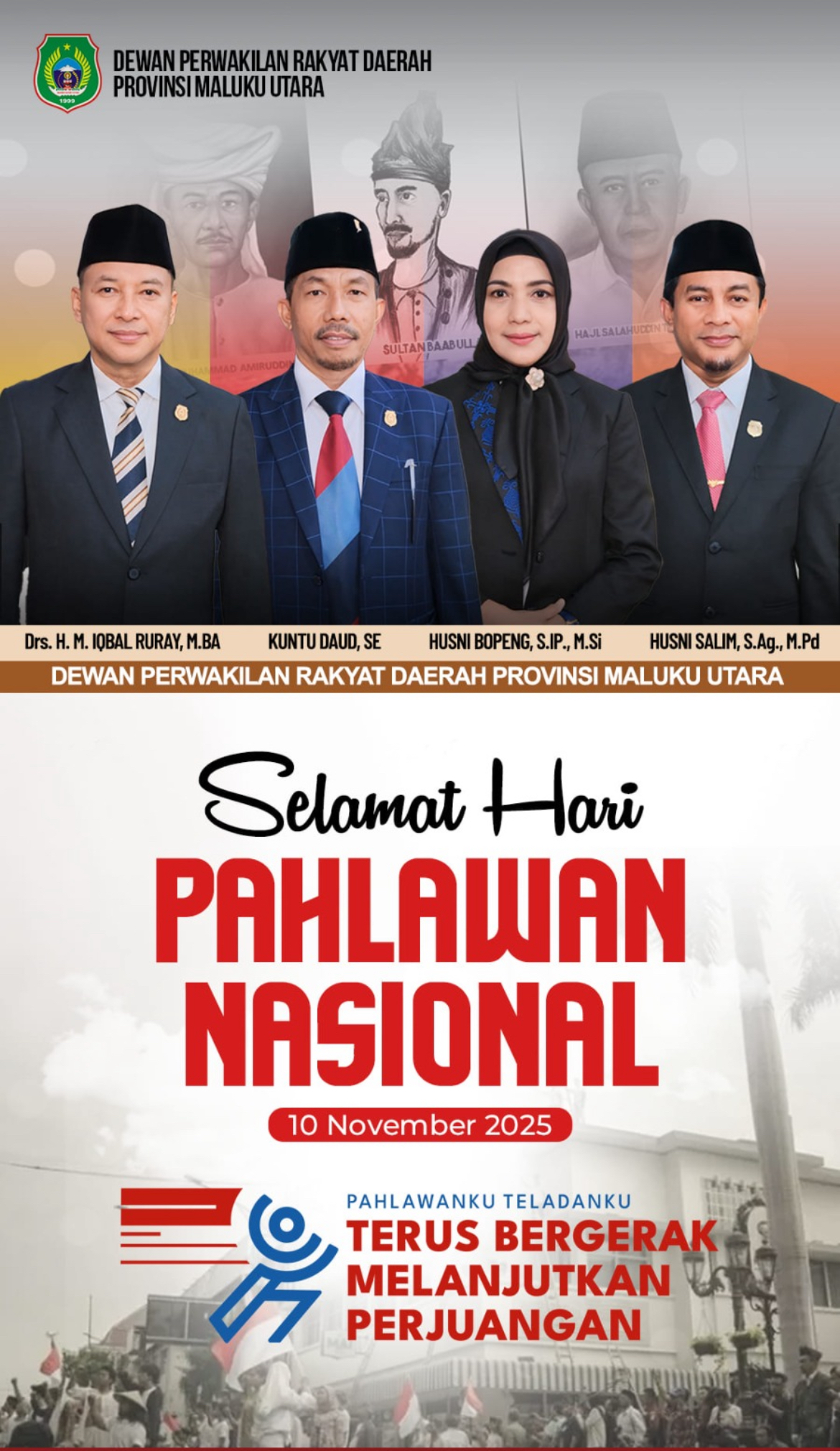TEKNOPOLITIK

Herman Oesman
Dosen Sosiologi FISIP UMMU
Dalam era serba digital yang kian maju, hubungan antara teknologi dan politik makin kompleks, rumit, dan saling mengikat. Salah satu pendekatan kritis yang menjelaskan hubungan ini adalah konsep teknopolitik (technopolitics).
Secara umum, teknopolitik merujuk pada cara teknologi digunakan secara sengaja untuk mencapai tujuan politik, serta bagaimana teknologi membentuk dan dibentuk oleh relasi kuasa dalam masyarakat.
Konsep teknopolitik pertama kali dikembangkan para ilmuwan ilmu sosial dan ilmu teknologi yang berusaha memahami bagaimana teknologi tidak pernah netral, tetapi selalu terikat pada nilai-nilai sosial dan kepentingan politik tertentu.
Sebut salah satunya, Paul N. Edwards dalam bukunya The Closed World…, menunjukkan bahwa sistem komputer dan teknologi informasi berkembang bukan hanya karena kemajuan teknis, tetapi juga karena agenda militer dan ideologi Perang Dingin (Edwards, 1996 : 10–11).
Hal ini memperlihatkan bahwa teknologi merupakan medan politik, bukan sekadar alat netral.
Teknopolitik bukan hanya berbicara tentang penggunaan teknologi oleh negara, melainkan mencakup berbagai aktor : perusahaan, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, bahkan individu. Teknologi menjadi medan kontestasi politik, baik dalam bentuk pengawasan, pengendalian informasi, maupun resistensi digital.
Dalam kerangka teknopolitik, teknologi dapat dilihat sebagai alat yang memperkuat atau memperlemah kekuasaan.
Tentang hal ini, telah lama diingatkan Michel Foucault (2007), tentang bagaimana teknologi, termasuk teknologi sosial seperti statistik atau sensus, menjadi alat governmentality, cara negara “mengatur” warga negara melalui pengumpulan data dan pengawasan.
Kini, dengan kemunculan kecerdasan buatan, sistem pengenalan wajah, dan algoritma big data, kemampuan negara dan korporasi untuk mengendalikan dan mengarahkan perilaku masyarakat makin tinggi. Shoshana Zuboff menyebut fenomena ini sebagai surveillance capitalism, yaitu kapitalisme yang memanfaatkan data pribadi individu untuk keuntungan ekonomi dan kontrol sosial (Zuboff, 2019 : 8).
Teknopolitik bukan hanya soal dominasi. Teknologi juga bisa menjadi alat perlawanan. Internet dan media sosial telah menjadi ruang bagi gerakan sosial untuk menyebarkan informasi alternatif, membangun solidaritas, dan menantang narasi dominan. Misal, Gerakan Arab Spring (2011), protes Hong Kong (2019), hingga perjuangan beberapa daerah untuk DOB lewat media digital, merupakan contoh bagaimana aktivisme digital menjadi bentuk teknopolitik dari bawah.
Menurut Manuel Castells, gerakan sosial abad ke-21 sangat bergantung pada jaringan digital. Dalam bukunya, Networks of Outrage and Hope, Castells menyatakan bahwa ruang digital telah menjadi medan utama pertarungan politik dan sosial, yang oleh Castells disebut sebagai *networked movements* (Castells, 2012 : 6–7).
Aktivis memanfaatkan media sosial tidak hanya untuk komunikasi, tetapi juga untuk mobilisasi dan membangun identitas kolektif.
Namun, penggunaan teknologi yang dilakukan masyarakat sipil juga menghadapi tantangan. Sensor, algoritma bias, dan manipulasi digital (seperti hoaks dan deepfake) acapkali mereduksi potensi demokratis dari teknologi.
Olehnya itu, teknopolitik selalu merupakan medan yang dinamis dan penuh konflik antara berbagai kepentingan.
Pertanyaan besar dalam perdebatan teknopolitik adalah : apakah teknologi memperkuat demokrasi atau justru melemahkannya?
Beberapa pihak optimistis bahwa teknologi digital membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. E-voting, transparansi anggaran digital, dan partisipasi warga melalui platform daring menjadi contoh bagaimana teknologi bisa memperkuat praktik demokrasi.
Namun oleh para kritikus, seperti Evgeny Morozov memperingatkan bahwa optimisme ini kerap menjadi naif. Dalam bukunya The Net Delusion, Morozov menyatakan bahwa otoritarianisme digital merupakan ancaman nyata, di mana teknologi yang semula dianggap pembebas justru menjadi alat represif (Morozov, 2011 : 5–6).
Dalam konteks Indonesia, teknopolitik terlihat dalam banyak aspek : dari penggunaan big data dalam pemilu, walaupun masih memiliki banyak kelemahan, lalu algoritma media sosial yang memperkuat polarisasi politik, hingga pengawasan digital terhadap aktivis dan jurnalis. Teknologi digital telah menjadi arena baru kontestasi politik, yang menuntut literasi digital dan kesadaran kritis dari masyarakat.
Teknopolitik merupakan lensa penting untuk memahami dunia kontemporer yang dibentuk oleh teknologi dan kekuasaan. Teknologi tidak netral, dan selalu beroperasi dalam kerangka politik tertentu. Dengan memahami teknopolitik, kita bisa lebih waspada terhadap cara teknologi digunakan, baik untuk menindas maupun membebaskan.
Di tengah pesatnya perkembangan digital, kesadaran teknopolitik menjadi kunci untuk menjaga demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial di era digital.[]