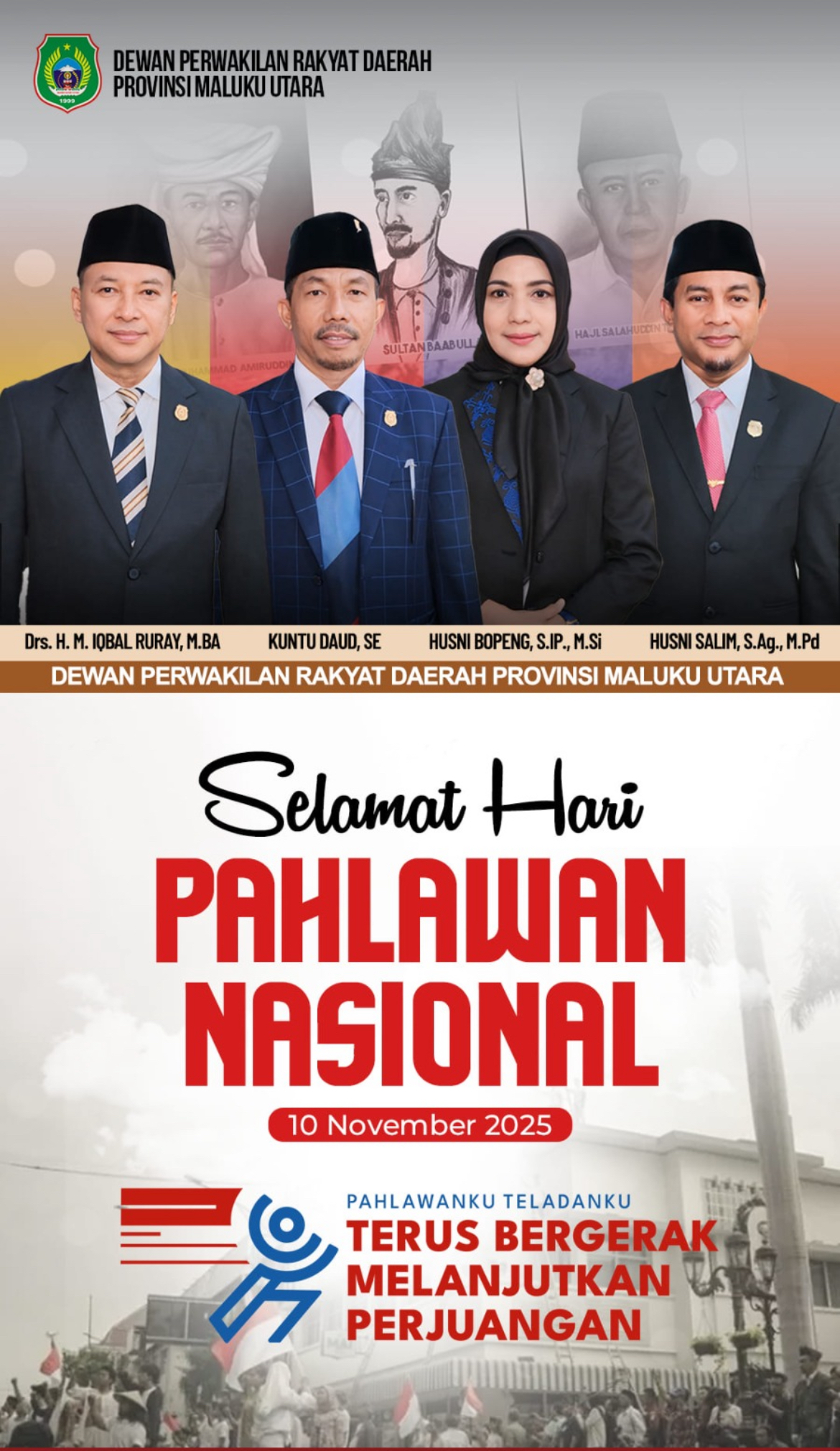Mengetahui dan Memahami

Herman Oesman
Dosen Sosiologi FISIP UMMU
“…memahami merupakan bentuk tertinggi dari mengetahui…untuk membangun dunia yang lebih bijaksana.”
Dalam ranah filsafat dan ilmu pengetahuan, terdapat dua istilah sangat penting yang kerapkali terdengar sepele namun sarat makna, yakni : “mengetahui” dan “memahami.” Keduanya merupakan aktivitas kognitif yang menjadi fondasi dari proses pembentukan pengetahuan manusia. Meski kerap dipakai secara bergantian, mengetahui (knowing) dan memahami (understanding) sebenarnya memiliki kedalaman makna dan implikasi yang berbeda. Keduanya merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan intelektual dan praksis sosial kita.
Mengetahui merupakan tindakan kognitif dasar yang berkaitan dengan pengenalan terhadap fakta, informasi, atau data. Dalam pengertian klasik yang diajukan oleh Plato, pengetahuan (episteme) didefinisikan sebagai “justified true belief”, keyakinan yang benar dan dibenarkan (Plato dalam Theaetetus, diterjemahkan M.J. Levett, 1992 : 98d).
Dengan kata lain, seseorang dikatakan mengetahui sesuatu apabila ia percaya terhadap suatu pernyataan, pernyataan itu benar, dan ia memiliki alasan atau bukti yang cukup untuk meyakini kebenarannya.
Sebagai contoh, seseorang dapat mengatakan bahwa ia “mengetahui” bahwa suatu objek yang panas mendidih berada pada suhu 100 derajat Celsius, karena ia telah membaca, mengamati, atau menguji fakta itu. Mengetahui di sini mencakup pencapaian kognitif minimal yang memungkinkan seseorang mengakses dan menyimpan informasi dalam ingatan.
Namun, knowing cenderung bersifat deskriptif. Ia tidak serta-merta menjamin bahwa orang tersebut dapat menjelaskan mengapa atau bagaimana sesuatu terjadi. Di sinilah batas mengetahui mulai terlihat ketika dibandingkan dengan memahami.
Memahami merupakan bentuk pencapaian pengetahuan yang lebih dalam dibanding sekadar mengetahui. Memahami ini dalam ilmu sosial dikenal dengan istilah verstehen dari Max Weber.
Menurut filosofi hermeneutik Hans-Georg Gadamer, memahami tidak hanya mengacu pada aktivitas mental, tetapi juga keterlibatan subjektif dalam menginterpretasi makna melalui konteks historis dan kebudayaan (Gadamer, 2004 : 282).
Dalam pengertian ini, memahami mengimplikasikan hubungan antara subjek dan objek yang bersifat dialogis dan reflektif.
Memahami bukan sekadar mengetahui bahwa sesuatu benar, tetapi mencakup penelusuran terhadap struktur, konteks, dan relasi antara elemen-elemen yang membentuk kebenaran tersebut. Misalnya, seseorang tidak hanya “mengetahui” bahwa krisis iklim sedang terjadi, tetapi “memahami” dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang menyebabkan krisis itu, dari konsumsi energi fosil, ketimpangan global, hingga model pembangunan kapitalistik.
Sementara dari pendekatan pedagogis, Benjamin Bloom dalam taksonominya membedakan antara “knowledge” dan “comprehension” sebagai dua level berbeda dalam proses belajar. “Knowledge” merupakan kemampuan mengingat fakta, sedangkan “comprehension” merupakan kemampuan menginterpretasi, menjelaskan, dan menyimpulkan informasi (Bloom, 1956 : 89).
Di era digital saat ini, fenomena knowing without understanding kian meluas. Akses terhadap informasi begitu mudah, tetapi pemahaman terhadap informasi tersebut kerapkali dangkal. Individu dapat mengetahui banyak fakta melalui mesin pencari, tetapi gagal memahami konteks atau makna di baliknya. Nicholas Carr mengkritik kecenderungan ini dalam bukunya The Shallows, dengan menyebut bahwa internet mengubah cara otak manusia menyerap informasi, lebih cepat, tetapi lebih dangkal (Carr, 2010 : 115).
Fenomena ini berdampak serius dalam ranah sosial-politik, terutama dalam penyebaran disinformasi. Orang-orang dengan mudah mengetahui “apa yang terjadi” melalui berita viral, tetapi gagal memahami kompleksitas peristiwa, sehingga mudah terprovokasi atau disesatkan.
Transformasi dari mengetahui menjadi memahami menuntut proses refleksi kritis, sebagaimana ditekankan Paulo Freire, yang menyatakan, pentingnya pendidikan yang membebaskan, yaitu pendidikan yang mengajak subjek belajar untuk tidak hanya mengetahui realitas, tetapi memahaminya secara kritis demi mengubahnya (Freire, 1970 : 72). Mengetahui tanpa pemahaman hanya akan menimbulkan kesadaran palsu, sedangkan pemahaman sejati akan menumbuhkan kesadaran kritis (conscientizacao).
Dalam praktik pendidikan, hal ini berarti mendorong pembelajar untuk tidak hanya menghafal materi, tetapi menelusuri makna, mengajukan pertanyaan, dan mengaitkan materi dengan konteks hidup mereka. Pendekatan konstruktivistik dalam pendidikan pun mengarah ke prinsip ini, yaitu membangun makna secara aktif melalui interaksi antara pengalaman dan pengetahuan (Piaget dalam Duffy & Cunningham, 1996 : 170).
Mengetahui dan memahami merupakan dua tingkat epistemik yang harus dipadukan secara harmonis. Mengetahui memberi kita dasar, tetapi memahami memberi kita makna. Dalam dunia yang penuh informasi seperti hari ini, tugas manusia bukan sekadar menjadi pengumpul fakta, melainkan menjadi pencari makna. Di sinilah pentingnya mengembangkan epistemologi yang humanistik, yaitu cara berpengetahuan yang tidak hanya rasional, tetapi juga reflektif dan etis.
Sebagaimana diungkapkan oleh Jiddu Krishnamurti, “mengetahui bukan berarti memahami. Mengetahui berarti memiliki informasi; memahami berarti mengubah”
(Krishnamurti, 1969 : 23).
Dengan demikian, memahami merupakan bentuk tertinggi dari mengetahui, dan keduanya merupakan langkah penting dalam membangun dunia yang lebih bijaksana.[]
BACA JUGA:Sosiologi Sebagai Kisah Manusia