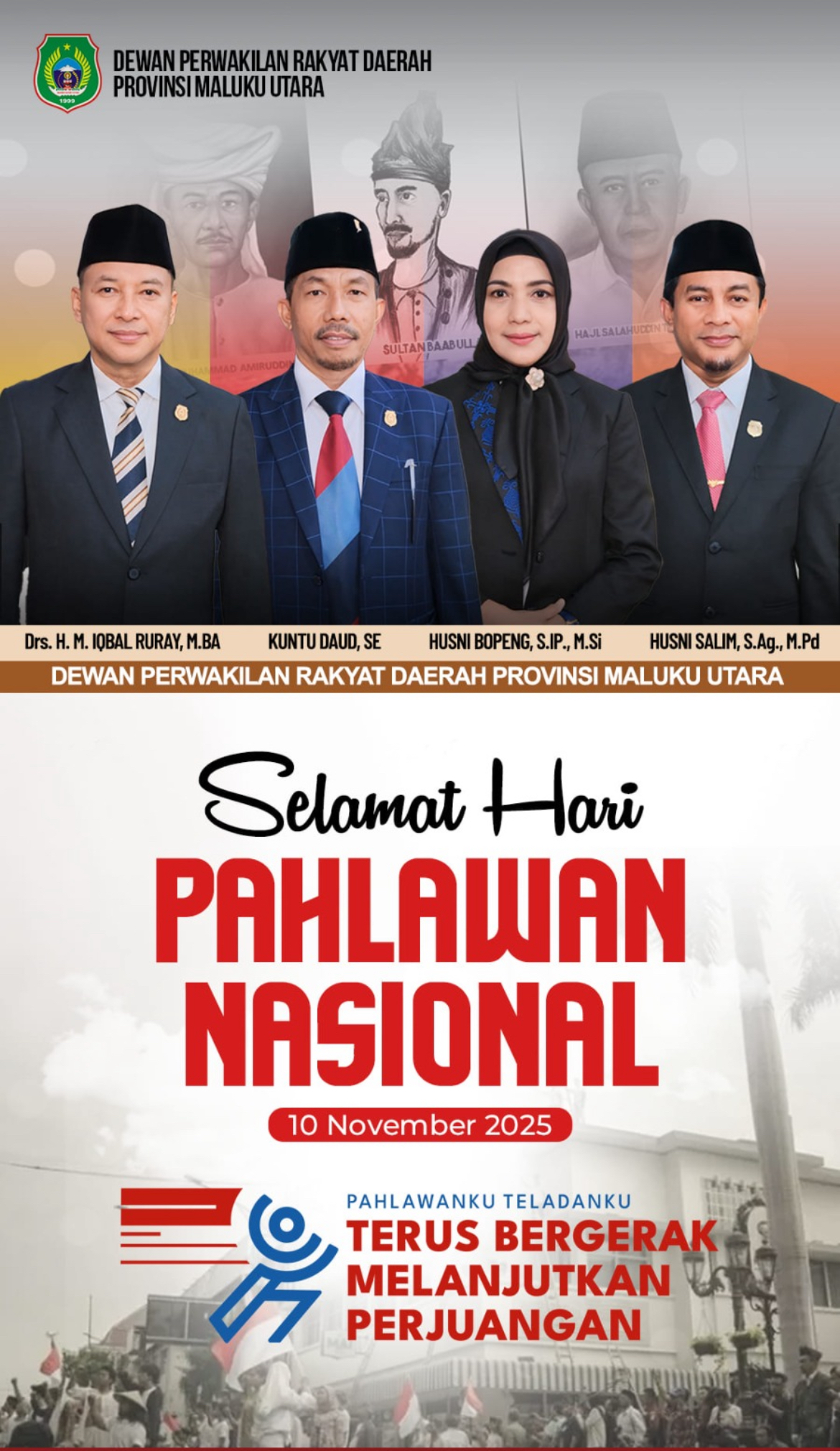Memahami Kurban dalam Sosiologi

Herman Oesman
Dosen Sosiologi FISIP UMMU
Idul Adha merupakan salah satu hari raya besar dalam Islam yang dirayakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Perayaan ini dikenal luas dengan ibadah kurban, yakni penyembelihan hewan seperti sapi, kambing, atau domba sebagai suatu bentuk ketaatan kepada Allah SWT.
Dimensi kurban tidaklah terbatas pada makna ritual penyembelihan belaka. Ia menyimpan dimensi spiritual, sosial, bahkan kritik terhadap ketimpangan ekonomi dan gaya hidup konsumtif masyarakat kontemporer.
Akar historis kurban terletak pada kisah Nabi Ibrahim A.S. dan putranya, Ismail A.S., yang menjadi simbol puncak ketaatan kepada perintah Ilahi. Dalam Al-Qur’an disebutkan :
“Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata: ‘Wahai anakku! Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu!’ Ia menjawab: ‘Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu; inshaa Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar’” (QS. As-Saffat [37]: 102).
Kisah tersebut menggambarkan nilai spiritual tertinggi dalam Islam: Tauhid (pengesaan Tuhan), Keikhlasan, dan Kepasrahan. Ibadah kurban bukan semata-mata ritual, melainkan refleksi dari kesiapan individu untuk mengorbankan apa yang dicintainya demi menaati Tuhan. Tentang hal ini, cendekiawan Muslim, Fazlur Rahman, menyebutkan, agama dalam Islam merupakan “a commitment to an ethical monotheism” yang menuntut pengorbanan etis dan personal, bukan hanya ritual simbolik (Rahman, 1982 : 48).
Aspek sosial dari ibadah kurban menjadi ciri penting dari perayaan Idul Adha. Dalam pelaksanaannya, daging kurban dibagikan kepada kaum dhuafa, tetangga, dan keluarga. Rasulullah SAW. bersabda: “Makanlah dagingnya, simpanlah, dan bersedekahlah darinya” (HR. Muslim No. 1971).
Hal ini menunjukkan bahwa kurban bukan sekadar bentuk pengabdian individual, melainkan ekspresi empati dan distribusi kesejahteraan. Dalam konteks ini, kurban menjadi medium untuk memperkuat solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan, serta mempertemukan kelompok yang selama ini mungkin terpisah oleh status sosial atau ekonomi.
Penulis terkemuka, Karen Armstrong menyebutkan, bahwa praktik keagamaan yang bersifat pengorbanan acapkali dimaksudkan untuk menyatukan komunitas dan membangun rasa kesalingterikatan (Armstrong, 2006 : 27).
Dalam masyarakat Muslim tradisional, distribusi daging kurban juga memiliki dimensi budaya yang kuat. Di desa-desa dan komunitas marjinal, momen ini merupakan satu-satunya saat dalam tahun di mana mereka dapat merasakan daging dalam jumlah cukup. Dengan demikian, ibadah kurban tidak dapat dilepaskan dari makna keadilan distributif dalam Islam, sebagaimana ditekankan dalam konsep ‘adl dan ihsan (lihat Nasr, 2002 : 103).
Sayangnya, dalam masyarakat modern, praktik kurban kerap bergeser menjadi arena prestise sosial. Hewan-hewan kurban dikompetisikan dari sisi harga, ukuran, dan jumlah, yang menjauh dari semangat kesederhanaan dan pengorbanan. Dalam perspektif sosiologi tentang hal ini, Sosiolog Muslim, Ali Shariati, melalui bukunya Hajj (Haji), menyatakan, bentuk-bentuk ibadah seperti kurban bisa menjadi kosong makna jika tercerabut dari tujuan transformatifnya. Shariati menulis :
“Ibadah yang sejatinya membebaskan manusia dari ego dan dunia, justru bisa menjadi alat penghiburan kosong jika tidak dikaitkan dengan perjuangan sosial” (Shariati, 1988 : 65).
Dengan demikian, kurban dalam masyarakat kapitalistik bisa menjelma menjadi ajang eksibisionisme religius. Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut oleh Jean Baudrillard sebagai “simulacra,” di mana simbol-simbol agama kehilangan makna asli dan menjadi konsumsi visual semata (Baudrillard, 1998 : 23).
Kembali pada spirit awalnya, kurban merupakan ibadah yang mengakar pada nilai-nilai ketulusan, keadilan sosial, dan pembebasan manusia dari keterikatan duniawi. Menariknya, dalam beberapa komunitas Muslim kontemporer, terdapat inisiatif untuk menyalurkan dana kurban dalam bentuk pembangunan ekonomi produktif bagi fakir miskin—bukan hanya konsumsi sesaat. Model seperti ini berupaya menjawab tantangan zaman sekaligus tetap memelihara esensi kurban.
Kurban dalam Idul Adha bukanlah sekadar ritual tahunan, melainkan panggilan spiritual dan sosial yang mendalam. Ia mengajarkan ketaatan total kepada Ilahi Rabbi, kepedulian terhadap sesama, dan kritik terhadap gaya hidup berlebih-lebihan. Dalam dunia yang semakin terdiferensiasi dan terpolarisasi secara sosial dan ekonomi, makna kurban perlu terus dihidupkan sebagai pengingat akan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang menjadi inti ajaran Islam.[]
BACA JUGA:SAJAK UNTUK MASYARAKAT TAMBANG