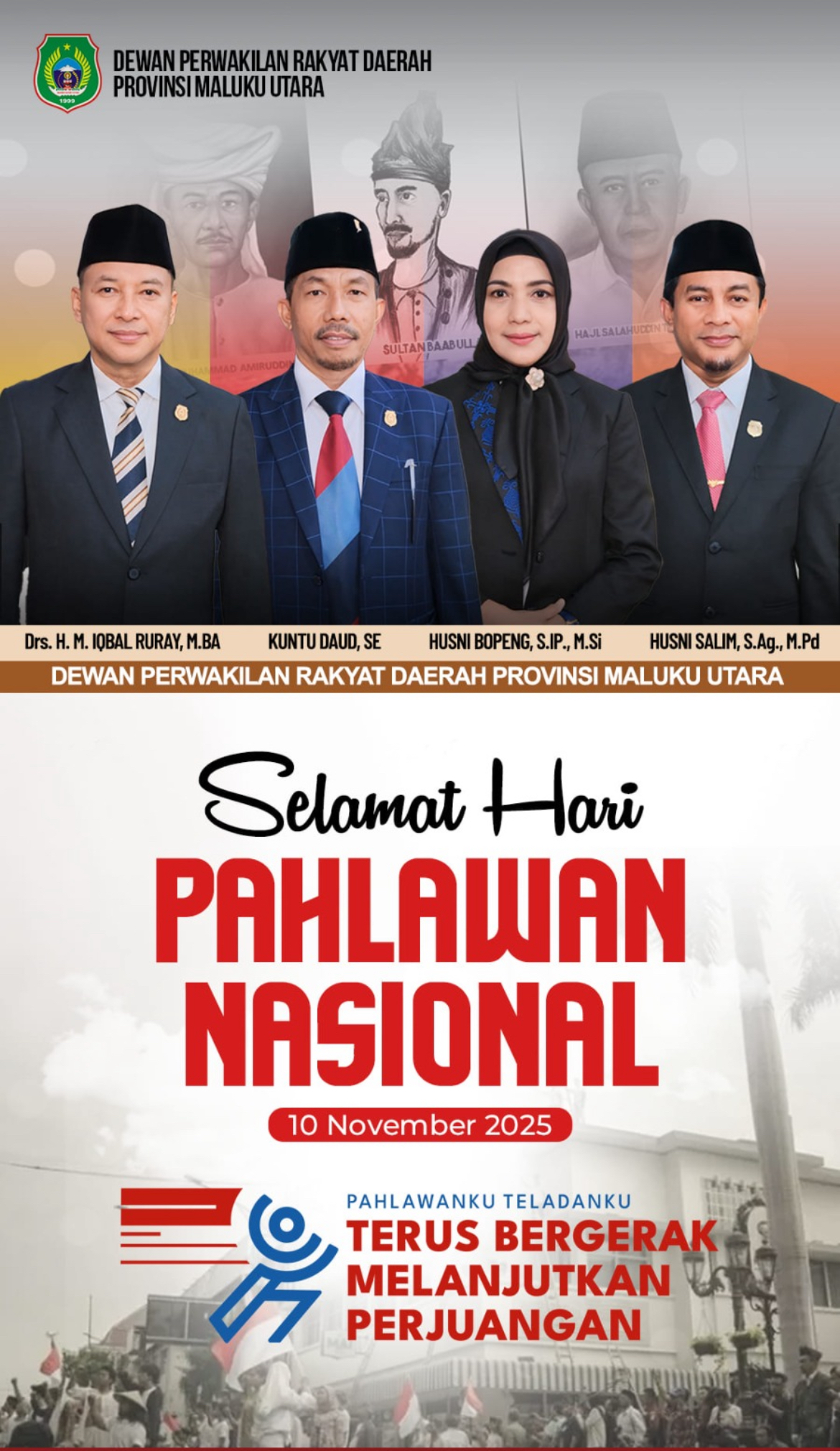INVOLUSI MASYARAKAT LAUT-PULAU
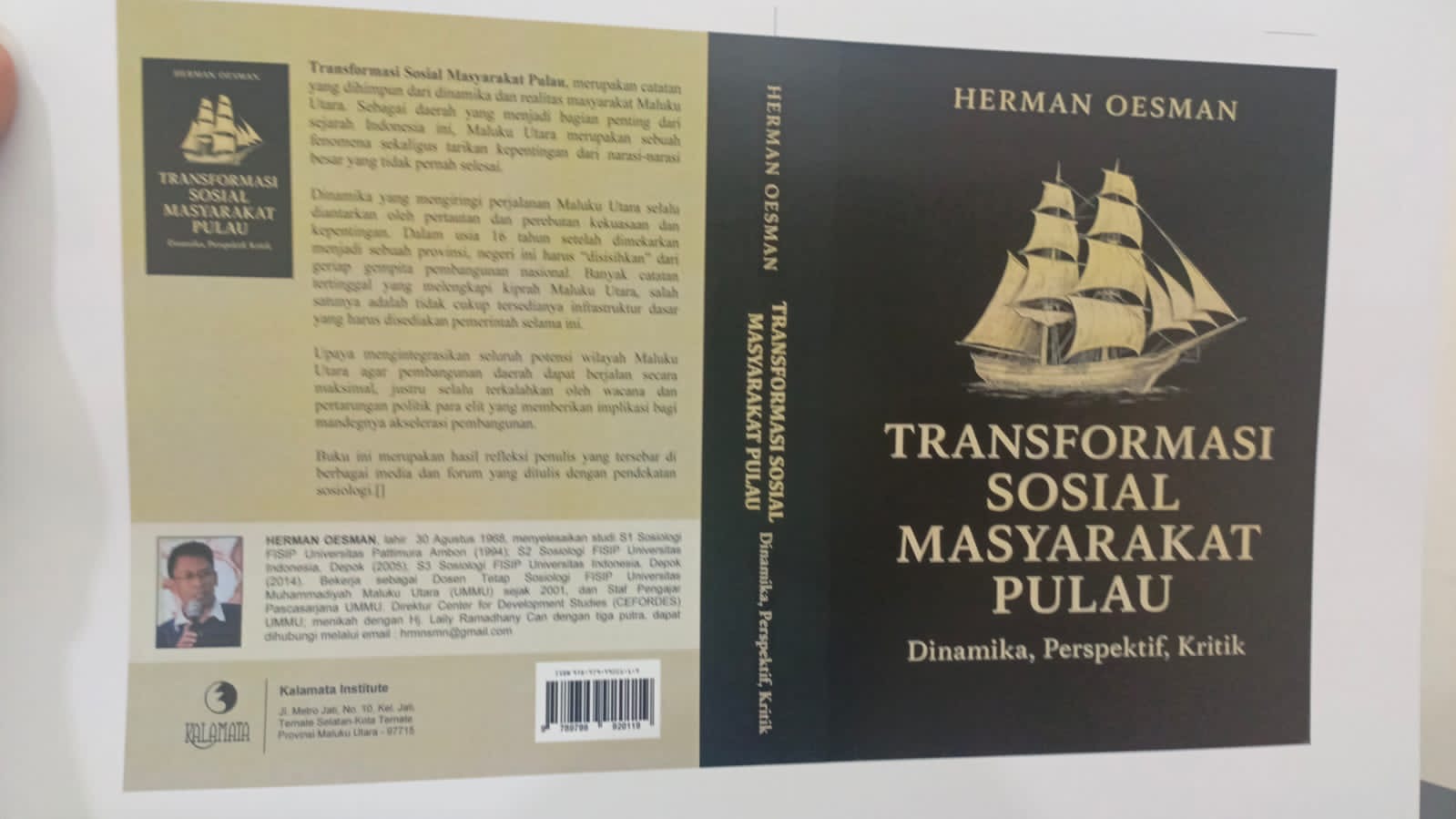
Dr. Herman Oesman
Transformasi Sosial Masyarakat Pulau Dinamika, Perspektif, Kritik Ternate, Penerbit Kalamata Institute, 2017, xxxiii + 605 halaman
A.Malik Ibrahim
“…terlalu lama negeri ini terpuruk dalam kubangan ketidak-berdayaan, hanya karena ketololan dan ketidak-pahaman akanpotensi yang kita miliki”, (hal 501).
Kata para filosof, pengetahuan adalah kebajikan. Hal itu sudah diketahuiorang semenjak sebelum Socrates. Tetapi bahwa pengetahuan adalah kekuasaan (knowledge is power) baru menjadi tegas semenjak Francis Bacon. Barangkali saja kalimat itu bukanlah penemuannya, dan mungkin pula beberapa pendahulu sebelumnya telah mengajarkannya; tetapi adalah Bacon yang memberinya suatu tekanan dan makna khusus, yang kita warisi sampai hari ini, terutama dalam paham teknokrasi.
Penjelasan yang paling sistematis dari filsafat Bacon adalah menguraikan sebab akibat atas peristiwa kausalitas. Ia memberi keunggulan pada manusia untuk mengatasi kekuatan-kekuatan alam melalui penemuan dan penciptaan ilmu pengetahuan. Dengan cara itu, Bacon telah mengucapkan selamat tinggal pada skolastisisme yang menjadikan filsafat sekedar sebagai pelayan teologi dan membaptisnya untuk tugas baru sebagai pelayan ilmu. Dengan demikian, efficient causes menjelma menjadi technical know how, ilmu menjadi teknik dan pengetahuan menjadi kekuatan rasionalitas-nilai dalam melakukan social engineering (lihat Kleden, 1987 : 85).
Dapat dikenali, bahwa basis praktis filsafat empiris adalah pendekatan yang memberi kita tafsiran terhadap beragam fakta. Tapi orang juga tidak bisa diyakinkan sekedar sebuah fakta, tanpa pertanyaan “epistemik” dari pandangan dasar pengetahuan ilmiah. Letak perbedaan utama antara filsafat sosial yang mendahuluinya dengan sosiologi modern adalah pada metodologi dan kausalitas sosial. Sebagai akibatnya, sosiologi ilmu pengetahuan kini tidak hanya menyampaikan temuan-temuan substantif tentang sifat hubungan sosial, tetapi juga terlibat dalam usaha untuk merumuskan kembali gagasan-gagasan kunci seperti “sosial, civil society dan ruang serta perjuangan untuk bertahan survival of the fittest”.
Ketika orang berbicara tentang “legitimasi keilmuan” akademisi, Herman Oesman memberi lanskap dalam perspektif itu. Buku yang diberi judul “Transformasi Sosial : Masyarakat Pulau – Dinamika, Perspektif, Kritik”, diasepertinya telah menyajikan nubuat tentang masa depan Maluku Utara, yang disebutnya sebagai “peta jalan” dalam mengawali studi pengembangan masyarakat pulau. Meski, pendekatan yang digagas – lebih bersifat taksonomi deskriptif pengembangan lokal, tetapi elemen endogenous yang dikaji dalam kehidupan sosial masyarakat pulau sangat terkait dengan sistem perwilayahan yang lebih luas.
Mengapa Masyarakat Pulau?
Salah satu pertimbangan dan pilihan strategis Herman dalam diskursus masyarakat pulau adalah keinginannya untuk membangun analisis kelembagaan modern (dalam pengertian sosiologis). Sebuah perspektif tentang “cara pandang orang pulau”, serta bagaimana realitas, dinamika dan sikap masyarakat dalam merespon perubahan? Dalam konteks pembangunan misalnya, seolah-olah masyarakat pulau adalah bagian dari masyarakat desa. Padahal sesungguhnya ada perbedaan dalam sikap, persepsi dan watak egalitarian – khususnya kemampuan beradaptasi dengan dunia luar.
Per definisi, sebagaimana diungkapkaan oleh Friedmann (1979), bahwa suatu pulau, daerah, region, kawasan, area, ruang, space atau lokalitas wilayah adalah suatu entitas yang mempunyai ciri-ciri dan keadaan berbeda. Tidak ada batasan spesifik dalam pengertian itu, selain aspek adminstratif dan fungsional. Intensitas proses pengembangan lokal (local development) lebih bersifat meaningful, karena adanya sosial krusial terkait dengan penumbuhan elemen-elemen lokal. Secara fungsional dan spasial perspektif masyarakat pulau dalam konteks ini lebih menekankan pada interaksi antarmanusia dengan sumberdaya lainnya.
Dari sana muncul kemudian pertanyaan: apakah konsep masyarakat pulau seperti sikap, kepribadian dan pola interaksi merupakan suatu konsep tentang Sollen atau konsep tentang Sein? Secara kontras, apakah local development sebagai konsep sosiologi atau politik perencanaan yang selama ini mengabaikan modal sosial (social capital), yang pada gilirannya dapat menciptakan kesenjangan wilayah (regional disparity), sebagai akibat dari kebocoran dan pengurasan sumberdaya lokal?.
Di sini perkembangan keadaan tidak bisa sekedar dijelaskan dengan teori perencanaan wilayah, sebagaiman beberapa konsep yang sering dipandang utopian, misalnya, Selective spatial closure, Development from below, Territoriality dan Agropolitan (Firman, 1997 : 64). Terutama jika dikaitkan dengan kepentingan studi masyarakat pulau yang lebih luas, karakteristik region Maluku Utara memiliki banyak kemiripan dengan wilayah frontier (frontier region). Dimana sumberdaya alam yang dieksploitasi dalan skala besar untuk kepentingan global, namun masyarakat justru terpinggir – dan menjadi aktor terlemah dalam relasi kekuasaan pengelolaan sumberdaya.
Menurut Herman, ini terjadi karena lemahnya institusi sosial. “Kemiskinan, baginya adalah arena (field) pertarungan antara pemodal dan pemilik kuasa, (hal 85). Darat (pulau) memang sudah menjadi modal yang hampir habis dijadikan tukar guling kepentingan dengan negara kaya”, (hal 488). Sebagai pembanding, dalam teori sosologi perubahan, kita mengenal kelompok sosial yang disebut “manusia pedalaman dan manusia pesisir. Di mana kemampuan berdaptasi secara cepat justru ada pada manusia pesisir yang berinteraksi secara rutin dengan parapendatang. Sedangkan masyarakat pedalaman punya kecenderungan “mempertahankan tradisi” (Kayam, 1989 : 15. Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir sangat cepat mengadopsi hal-hal baru. Sementara orang pedalaman cenderung terkurung dan hanya berkutat dengan dunia internalnya.
Masyarakat pulau dalam konteks sosiologi kepulauan, menurut penulis merupakan realitas dengan ciri khusus, seperti : Pertama, egaliter; yaitu sikap bersahaja dan terbuka dalam berinteraksi. Kedua, altruistik; mengutamakan kepentingan bersama. Ketiga, soliditas; rukun dan jauh dari resistensi sosial. Keempat, interpersonal trust; kuatnya budaya saling percaya. Dan kelima, relijius; tingginya ketaatan dalam menjunjung nilai-nilai agama dan kepercayaan, (hal xxx).
Dalam persepsi sosiologis, orientasi nilai budaya masyarakat pulau, tentu masih perlu diperdebatkan atau dibuat deferensiasi yang sesuai dengan dinamika transformasi sosial, apakah sebagai tindakan atau pemahaman, termasuk kemungkinan penelitian lebih lanjut.
Menoleh ke Laut-Pulau
Gagalnya mainstreaming masyarakat laut-pulau – terlihat dari berbagai kebijakan selama ini,yang tentunya masih berorientasi ke darat. “ Sebagai daerah kelautan dan kepulauan, kondisi tersebut tentu seringkali membuat program pembangunan yang dilaksanakan hanya terfokus pada satu atau beberapa pulau tertentu, dengan alokasi program yang tidak memperhatikan keutuhan dan keterpaduan program dalam satu kesatuan tata ruang (hal, 486). Definisi pulau pun ditetapkan dengann mengacu pada ketentuan United Nation Convention the Law of the Sea (UNCLOS)1982, yang menyatakan bahwa “pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alami dikelilingi oleh air dan ada di atas permukaan air pada saat air pasang”.
Apakah ini bagian dari warisan sejarah masa lalu, dimana laut lebih sekedar dianggap sebagai faktor pembatas atau pemisah? Akibatnya muncul dikotomi antara “orang pedalaman dan orang pesisir, budaya gunung dan budaya seberang, karena laut tak dipandang sebagai penghubung antar pulau. Kenyataan ini jelas sangat memprihatinkan, padahal kita ketahui bahwa pulau-pulau di wilayah Maluku Utara telah dikelompokkan menjadi gugus pulau yang dibentuk berdasarkan kedekatan geografis, kesamaan budaya, kesatuan alam, kecenderungan orientasi , kesamaan ekonomi dan potensi sumber daya alam.
Tentunya diskursus tentang masyarakat pulau yang secara kritis ditawarkan Herman masih perlu diperdebatkan. Mungkin Herman benar, ketika mengatakan bahwa dibutuhkan mainstream (arus utama) pada kesadaran formulasi kebijakan dan program. Artinya, ada devolusi politik pengelolaan sumber daya masayarakat pulau, yang tidak terbatas hanya pada sistem ekologi, tetapi lebih pada inovasi kebijakan pengembangan sumber daya manusianya.
Dalam proses itu, terdapat beberapa hierarki persoalan dalam isu kepemimpinan daerah, terkait dengan pengetahuan dan kesadaran. Banyak pengambil keputusan gagal pada pilihan strategis dan lemahnya concern partai politik tentang problem masyarakat pulau. Belum masuknya kawasan laut-pulaudalam kesadaran politik yang membuat mengakibatkan banyak kebijakan yang tidak berpihak ke laut. “Selama ini, data korelasi antara luas laut dan isinya dengan tingkat kesejahteraan nelayan, belum menunjukkan nelayan itu sejahtera, atau pembangunan kepulauan itu mampu mandiri. Adakah wilayah pesisir kehidupannya persis sama dengan desa dan kota? Potensi darat kita keruk dengan hasil bumi dihabiskan (sumberdaya yang tidak bisa diperbaharui), adakah orang desa makmur dengan apa yang dikenal dengan CSR? Kita sekarang beralih ke laut, isi perut laut mulai kita pikirkan setelah sekian lama dijarah dan dicuri negara lain. Apakah laut akan bernasib sama dengan daratan yang setelah dikuras habis, yang hanya akan meninggalkan jejak-jejak penyesalan”?(hal 488-489).
Mengapa Maluku Utara terus dikutuk mendapatkan pemimpin yang tidak mampu berpikir dan memprioritaskan kebijakan pembangunan yang benar-benar penting dan mendesak di tengah keterbatasan anggaran? Sedikit sekali kebijakan pembangunan ekonomi yang dikaitkan dengan konsep tata ruang, terutama kluster wilayah pengembangan. Tidak ada inovasi pengembangan wilayah yang kemudian akan menjadi multipliereffect, yang menyebar ke pulau-pulau sekitar yang menyokong terciptanya backward linkages dan forward linkages suatu kawasan laut pulau.
Secara garis besar, meski buku ini dieksplorasi dari berbagai kumpulan tulisan yang tersebar di media dan forum, dapat ditarik suatu benang merah yang menjelaskan betapa penting transformasi masyarakat pulau. Lebih dari itu sumbangan pemikiran Herman Oesman kiranya dijadikan rujukan untuk mendalami dan memahami problematika dan realitas Maluku Utara dewasa ini. Semoga buku ini dapat memberikan ‘insight” yang membuat kita yakin bahwa profil pemimpin Maluku Utara ke depan, kata cinta saja tidak cukup, harus juga cerdas dan cermat.[]
BACA JUGA:SAJAK UNTUK MASYARAKAT TAMBANG